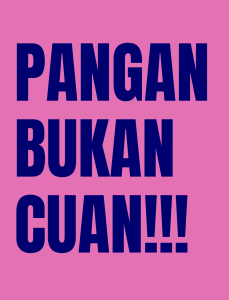Oleh Endriatmo Sutarto
(J)ika pemerintah punya kebijaksanaan berpandangan jauh, potensi golongan buruh tani (kepala keluarga) sebanyak itu di Jawa dapat dimobilisasi. Caranya? Dengan land reform!
Penghargaan Habibie Award 2011 untuk Profesor Sajogyo untuk kategori ilmu sosial pada 10 November 2011 adalah satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya pribadi sebagai salah seorang yang sangat beruntung mendapatkan kemewahan berinteraksi cukup intens dengan Profesor Sajogyo untuk waktu yang relatif panjang. Dalam hal ini, saya pernah berkiprah dalam beragam posisi akademis yang berbeda-beda di hadapan beliau. Dalam sudut pandang subyektif, tampak terlihat perguliran pemikiran Profesor Sajogyo yang datang dari waktu ke waktu, dari yang semua beraksen sosiologi pedesaan Indonesia yang empiris-kritis berlanjut menjadi sosiologi pedesaan Indonesia kritis-aplikatif bagi kebijakan dan praktek pembangunan pedesaan.
Profesor Sajogyo dikenal sebagai Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia atau Bapak Ekonomi-sosiologi Indonesia sebagaimana oleh Profesor Mubyarto, yang bukan hanya meletakkan fondasi bagi tersedianya pengetahuan, alat-alat konseptual, dan pendekatan yang memadai untuk memahami perubahan agraria di pedesaan Indonesia, lebih dari itu, menunjukkan bagaimana sosiologi pedesaan Indonesia dapat memberi sumbangan konkrit yang layak dan bisa dikerjakan oleh para praktisi pembangunan pedesaan. Beliau telah menunjukkan cara bagaimana kelangkaan pengetahuan tentang masalah-masalah agraria di Indonesia, khususnya mengenai kehidupan lapisan terlemah di pedesaan, dapat diisi dengan penelitian dan keterlibatan langsung secara partisipatif bersama mereka yang lemah itu, sekaligus mengembangkan kemampuan berdialog dengan segenap pihak yang memberi pengaruh bukan hanya pada kalangan akademisi, tapi juga para praktisi lapangan dan pemegang kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, mudah dimengerti jika sosiologi pedesaan Sajogyo dapat diterima dengan baik dalam proses-proses kebijakan di sejumlah badan pemerintahan.
Ilustrasi mengenai hal ini adalah andilnya kebijakan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Pada 1972, ia memimpin survey UPGK selama dua tahun dengan melibatkan peneliti-peneliti berbagai perguruan tinggi, bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UNICEF. Hasil kajiannya antara lain disajikan menjadi panduan para kader program Taman Gizi, yakni kumpulan orang yang berorganisasi meningkatkan gizi anak balita dan keluarga. Perhatiannya ini mengantarkannya menjadi Ketua Pergizi Pangan Indonesia pada 1978, yang berafiliasi dengan International Union of Nutrition Science. Dari riset UPGK ini pulalah pada 1977 ia merumuskan pengukuran garis kemiskinan: Garis Kemiskinan Sajogyo. Sumbangsih ini berhasil mengatasi kemacetan metodologis dalam menilai dan mengukur kemiskinan, satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan sosial. Pengukuran berdasarkan kecukupan pangan ini kemudian berkembang dan diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam rumusan lain sebagai food basket atau yang sering dikenal sebagai paket kebutuhan dasar pangan empat sehat lima sempurna.
Fokus dan tema gagasan Sajogyo selalu memperkaya dan mempertajam kerangka pembangunan yang diagendakan pemerintah serta berusaha mempengaruhi arah dan keberpihakannya. Namun tentu saja ia juga mengkritiknya dengan mengemukakan nasib golongan paling lemah di pedesaan. Di sinilah kita menyaksikan Profesor Sajogyo sangatlah peduli dan prihatin terhadap apa yang ditengarai oleh gurunya, Profesor W.F. Wertheim, sebagai sociology of ignorance dari kebanyakan akademisi Indonesia dalam memahami dan memposisikan lapis termiskin masyarakat pedesaan Indonesia, yaitu mereka tidak bertanah.
Karya klasiknya pada 1973 berjudul Modernization without Development in Rural Java melakukan evaluasi-kritik terhadap Revolusi Hijau. Telaah yang diajukan untuk acara badan dunia FAO di Bangkok ini menunjukkan Revolusi Hijau –di sisi lain kesuksesan dari swasembada beras waktu itu- ternyata hanya menguntungkan petani golongan atas dan mempercepat proses hilangnya akses terhadap tanah para petani gurem dan jatuhnya kebanyakan mereka menjadi lapis termiskin di pedesaan: petani tak bertanah. Karya ini menjadi rujukan utama dalam kajian Green Revolution yang terjadi di berbagai benua.
Selanjutnya, pada 1976, tatkala isu Reforma Agraria atau land reform masih dianggap tabu, Sajogyo secara halus tapi teguh mengusulkan kembali perlunya pemerintah memberikan akses permanen buruh tani di desa-desa pada tanah melalui program penyediaan tanah kolektif. Profesor Sajogyo menulis “..(J)ika pemerintah punya kebijaksanaan berpandangan jauh, potensi golongan buruh tani (kepala keluarga) sebanyak itu di Jawa dapat dimobilisasi. Caranya? Dengan land reform!”
Pada 1980, Sajogyo memberi kontribusi gagasan yang disebut dengan Ekologi Pedesaan. Melalui buku ini, beliau hendak menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa untuk memahami pedesaan di Indonesia, selain keniscayaan keragaman sejarah, karakteristik, serta lapisan dan dimensi sosial ekonomi dan budayanya, diperlukan pemahaman relasional yang baik antara “bentang alam” dan “bentang sosial” sebagai potret utuh pedesaan di Indonesia itu sendiri. Kedua, bahwa segala bentuk usaha untuk tujuan pembangunan ekonomi di pedesaan mesti bertumpu pada swadaya dan “tenaga dalam” yang ada di pedesaan. Artinya, dengan pemahaman semacam ini, Profesor Sajogyo ingin mengingatkan pentingnya memastikan keberlanjutan “siklus reproduksi” (sosial, ekonomi, dan budaya) di pedesaan.
Di akhir karier akademisnya sebagai intelektual paripurna, Sajogyo menuliskan suatu refleksi perjalanan hidupnya Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek Berteori. Dengan merujuk pemikiran Robet Chambers, beliau menunjukkan jalan hidupnya “mendahulukan yang terbelakang”, yang menurut saya ini uraian paling jelas mengenai kiprah Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia tersebut. Lebih dari itu, ia melintasinya dengan menganjurkan metode kerja praksis intelektual untuk perubahan nasib “golongan paling lemah” di pedesaan, yakni mengedepankan hubungan dialektika yang tak pernah henti antara teori dan praktek atau praktek dan teori.
Dalam perspektif bidang keilmuan yang ditekuninya, sosiologi pedesaan, Sajogyo mengajak para ilmuwan dan intelektual memiliki wawasan yang utuh dan komprehensif memahami masyarakat di Indonesia.Ungkapannya yang sangat popular, mewakili watak metodologis lain dari Profesor Sajogyo adalah, “If you want to understand the economy of my country… study my culture and our political system. If you want to understand our culture and political system… study our economy.”
Warisan intelektual Sajogyo adalah untuk masa depan studi agraria Indonesia. Untuk mendukung cita-citanya itu, pada 2005, para murid, pengagum, kolega, dan keluarganya berprakarsa mendirikan Sajogyo Institute, yang berkedudukan di Bogor. Profesor Sajogyo mewakafkan harta benda melalui lembaga ini. Ia tak henti-hentinya menjaga imajinasi dan selalu menyadarkan bahwa dunia agraris adalah pelahir Indonesia, penghidup bagi sekian juta penduduk, baik di desa maupun kota. Menyelamatkan Indonesia adalah membangun desa dengan segenap kedaulatan manusia dan alat-alat produksinya.
Cita-cita Sajogyo ini berkesinambungan dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Cita-cita itu adalah cita-cita besar kita semua, membangun Keindonesiaan yang Cerdas dan Merdeka: “slamatkan tanahnya, slamatkan puteranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya”.
Dimuat di Koran Tempo, Senin, 19 Desember 2011.