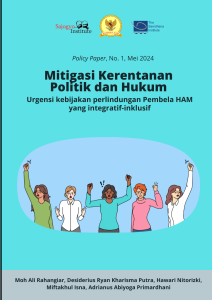Oleh: Siti Maimunah, Sarah Agustiorini – 5 Juni 2020
Andai mesin waktu bisa membawa kita mundur ke masa lalu mengunjungi Sungai Mahakam, sungai terpanjang kedua di Indonesia yang membelah Kalimantan Timur, kita akan menyaksikan perusahaan-perusahaan tambang minyak dan batubara beroperasi pada 1896 hingga 1899, lalu perusahaan kayu milik Belanda dan Jepang berjalan pada 1920-an. Kayu-kayu ulin tua itu diangkut melalui Sungai Mahakam menuju Makasar dan Singapura, untuk selanjutnya menuju Tiongkok dan Eropa.
Jika waktu kita majukan setengah abad berikutnya, di tempat yang sama, pemandangan masih serupa.
Rakit-rakit dari gelondongan kayu terapung sepanjang beberapa kilometer menuju pabrik-pabrik pengolahan di tepi sungai. Atau, barisan kapal-kapal tongkang membawa tumpukan kayu-kayu gelondongan ulin dan jenis meranti dari hutan alam untuk diangkut ke Jepang dan Eropa.
Dan, bila kita maju lagi di masa sekarang, pemandangannya beda tipis: Setiap hari di atas sungai yang sama, kita menyaksikan lalu-lalang 60 hingga 80 kapal tongkang berwarna cerah yang mengangkut batubara bergunung-gunung di atasnya. Tiap kapal mengangkut sekitar 7-8 ribu metrik ton batubara menuju pembangkit listrik tenaga batubara di Jawa dan Bali. Atau diangkut ke India, Cina, dan negara Asia Tenggara.
Maka, lebih dari 100 tahun, sungai ini telah diprivatisasi untuk kepentingan industri ekstraktif.
Sungai sebagai Ruang Hidup Bersama
Sungai seperti juga kawasan karts, hutan, laut dan lainnya merupakan ruang hidup bersama atau ‘the commons” (Giovanna Ricoveri, 2013). Ia adalah sumber daya pendukung kehidupan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsisten), bukan untuk dimiliki perorangan dan tidak untuk dijadikan komoditas (komodifikasi). Hubungan timbal balik alam dan manusia dalam the commons menghasilkan pengetahuan dan pengalaman, kerja sama dan ketergantungan timbal balik; bentuknya bergantung perbedaan tempat dan waktu.
Sungai Mahakam menjadi saksi tumbuh dan runtuhnya kebudayaan kerajaan Hindu Kutai (350-400 M) dan Kesultanan Islam Kutai Kartanegara (1300-1945), juga pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Kalimantan Timur sejak 1565. Keterhubungan manusia dan sungai dirayakan dalam pesta tahunan erau—syukuran atas hasil bumi penduduknya. Upacara ini berlangsung sejak abad 12, biasanya dirayakan selama 40 hari, ditutup dengan ritual belimbur atau mensucikan diri di sungai.
Samarinda, yang dibelah Sungai Mahakam, tumbuh menjadi kota pelabuhan dagang sejak 1700-an. Ia dinobatkan sebagai ibu kota provinsi pada 1959 dengan luas 71.800 hektare. Kota yang tumbuh bersama industri ekstraksi ini menjadi “godaan” bagi banyak orang dari luar pulau maupun sekitarnya datang ke sini.
Program transmigrasi maupun migrasi mandiri dari Pulau Jawa dan sekitarnya telah dimulai sejak awal kemerdekan. Para pendatang nantinya adalah sumber buruh murah bagi industri ekstraksi di Kalimantan Timur. Pada 2019, kota ini dihuni 858.080 jiwa atau 23,5% penduduk Kalimantan Timur, terpadat di provinsi ini.
Selain manusia, daerah aliran sungai (DAS) Mahakam merupakan ruang hidup bagi 298 jenis burung, 70 di antaranya dilindungi dengan 5 jenis endemik, juga habitat bagi 147 jenis ikan lokal air tawar, beberapa di antaranya endemik dan bermigrasi dari hilir ke hulu Mahakam setiap tahun. Ia juga rumah terakhir pesut (Orcaella brevirostris), lumba-lumba air tawar yang statusnya terancam punah karena habitatnya makin tercemar. Dua tahun lalu populasinya tersisa 80 ekor.
Privatisasi Berlapis Sungai Mahakam
Salah satu peranan penting negara adalah menyusun peraturan untuk mengatur pembagian dan memberi batas administrasi terhadap alam, termasuk daerah aliran sungai (DAS). Jika dianalogikan sungai seperti tubuh kita, maka tubuh Sungai Mahakam telah dibagi-bagi, di-administrasi-kan ke dalam 3 kabupaten dan 1 kota.
Hulu sungai Mahakam berada di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat, lantas badannya di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kakinya di Kota Samarinda. Politik pengaturan ini memudahkan ruang didata, dipetakan, dijadikan sumber uang, dan dibagi lagi ke dalam skala lebih kecil sesuai peruntukan yang direncanakan administrator, seperti bagian mana untuk hutan tebangan, hutan konservasi, lahan industri, perumahan dan lainnya. Inilah yang disebut Nancy Peluso dan Vandergaazt (2008) sebagai “proses teritorialisasi.”
Sebenarnya, teritorialisasi dan privatisasi ruang melalui pemberian konsesi migas, batubara dan kayu di Kalimantan Timur telah dimulai sejak masa kolonial. Namun ia bertambah masif dan sistematis dengan kehadiran negara. Perusahaan-perusahaan kayu menjadikan tepian Sungai Mahakam sebagai tepat penumpukan kayu (logpond) sebelum diangkut kapal-kapal tongkang ke luar dari Samarinda. Bersama industri migas, penebangan kayu menjadi sumber uang rezim Soeharto dan kroninya sebelum 1998.
Sejak 1968, tercatat 17 perusahaan pemegang HPH dengan luas ratusan ribu hektare menguasai hulu Sungai Mahakam. Pada 2009 sampai 2013 saja wilayah DAS Mahakam kehilangan hutan alam seluas 128 ribu ha akibat ekstraksi kayu, pertambangan, dan perkebunan skala besar (FWI, 2014). Hingga 2013, separuh hutan alam di DAS Mahakam hilang dan tinggal tersisa 4,1 juta ha.
Hutan yang terus menerus ditebang tapi hanya sebagian yang ditanami kembali, makin lama tak mampu memenuhi mesin-mesin pengolah kayu. Industri kayu meredup saat hutan Indonesia disebut sebagai negara dengan angka deforestasi paling tinggi di dunia pada 2008. Namun, mesin kapital selalu kreatif untuk bangkit dan berputar kembali. Naiknya permintaan batubara di pasar dunia membuat privatisasi ruang terus berlanjut melalui pemberian konsesi-konsesi tambang dan pengerukan batubara.
Sejak 2000-an, jumlah izin konsesi tambang batubara terus naik, khususnya menjelang atau sesudah Pilkada Samarinda. Proses izin menjadi sumber rente bagi para politikus nasional dan lokal untuk mendapatkan suara saat Pemilu maupun Pilkada. Sampai 2016, ada 747 konsesi pertambangan di sekitar Sungai Mahakam (Jatam, 2020). Sungai sebagai infrastruktur sosial-ekologis, yang diubah menjadi infrastruktur ekstraksi hutan, kini diganti mendukung industri batubara. Tepian sungai menjadi lokasi konveyor dan penumpukan (stockpile) batubara sebelum dipindahkan ke tongkang-tongkang dan diangkut melalui sungai untuk keluar dari Kalimantan Timur.
Ruang Sisa bagi Pengungsian Sosial-Ekologis
Ruang hidup sepanjang Sungai Mahakam bagaikan kantong pengungsian kota yang sejak lama melayani industri ekstraksi, dan hanya menyediakan ruang sisa bagi warga kota.
Ruang sisa (residual space) merupakan “sudut-sudut kota” yang masih bisa dipakai warga untuk melakukan penyesuaian hidup, wilayah-wilayah yang entah awalnya memang dirancang atau ditinggalkan. Sebagai wilayah yang tak direncanakan secara tertulis (unscripted), kepemilikannya pun lemah (Khalil MH & Eissa DM, 2013). Lebih dari itu, mereka bisa digusur dengan alasan menyebabkan kota menjadi kumuh maupun alasan konservasi.
Di Kota Samarinda ruang tersisa adalah permukiman kumuh di sepanjang Sungai Karang Asam dan Karang Mumus, ruang hijau kurang dari 1 persen, krisis air bersih, dan langganan banjir setiap tahun. Sejak 2008, pemerintah kota sudah mengumumkan akan menggusur permukiman kumuh di tepian sungai Karang Mumus dengan dalih mengurangi banjir dan demi penataan kota lewat pembangunan perumahan.
Pada ruang-ruang sisa ini peran negara lebih kelihatan, setidaknya melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Sudah 45 tahun PDAM Tirta Kencana melakukan komersialisasi air Sungai Mahakam kualitasnya memburuk dari waktu ke waktu. Penyebab awalnya, selain pasang surut air di muara sejak 1980-an hingga 1990, masalah utama sekarang adalah sedimentasi akibat industri ekstraktif sepanjang sungai. Meski begitu, di tengah ketidakpuasan pelanggan terhadap debit air terlalu kecil, air keruh, dan kadang hanya mengalir di malam hari bahkan mati hingga berhari-hari, PDAM masih berhasil mengeruk keuntungan sekitar Rp7 miliar pada 2018.
Dalam penelitiannya sejak 2009-211, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim menyebut kondisi Sungai Mahakam tercemar berat. Yayasan konservasi RASI, lembaga yang peduli pada keselamatan pesut, menemukan kandungan kadmium (Cd) dan timbal (Pb) di Sungai Mahakam melampaui ambang batas pada 2017-2018. Kondisi ini membuat PDAM meningkatkan penggunaan bahan kimia penjernih air.
PDAM menggunakan kaporit (kalsium hipoklorit), soda abu, aluminium sulfat, klorida dan kaolin sebagai bahan utama menjernihkan dan membunuh bakteri. Sebagian bahan-bahan ini bersifat karsinogenik atau memicu sel kanker jika terus menerus digunakan.
Bagaimana wilayah Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, dan Sambutan yang dihuni 28 persen populasi Kota Samarinda tapi sebagian besar tak terjangkau jaringan air PDAM karena jarak dan kondisi geografisnya?
Pada wilayah ini, telah banyak berubah daerah tangkapan dan simpanan airnya menjadi konsesi pertambangan batubara, bahkan berdekatan dengan permukiman warga. Selain itu, ada 394 lubang tambang yang ditinggalkan perusahaan pemiliknya tanpa direklamasi (JATAM, 2020). Sebagian lubang-lubang tambang ini telah menyebabkan sedikitnya 10 orang mati tenggelam dan tak satu kasus pun yang diusut hukum.
Warga di wilayah ini biasanya hanya punya tiga pilihan: mengonsumsi air dari lubang tambang, membuat sumur bor, atau membeli air tangki dan air galon.
Air dari lubang tambang tercemar, tapi terpaksa dikonsumsi oleh warga yang tak mampu membeli air. Sementara dua pilihan lain membutuhkan biaya tidak sedikit. Biaya pembuatan sumur bor tergantung tingkat kesulitannya, berkisar Rp3 juta – Rp5 juta.
Di musim kemarau, krisis air meluas ke wilayah perkotaan karena debit air Sungai Mahakam berkurang dan menyebabkan air PDAM makin tersendat mengalir ke rumah pelanggan. Para pelanggan PDAM terpaksa mengandalkan air tambahan dengan membeli air dari mobil tangki yang diantar ke rumah-rumah. PDAM justru melihat ini sebagai peluang untuk melipatgandakan keuntungan. Mereka menjual air tangki 1200 liter dengan harga sekitar Rp 200 ribu. Sementara harga air bukan dari PDAM, dengan ukuran yang sama, bisa lebih murah, sekitar Rp80 ribu. Warga percaya air PDAM lebih aman sehingga bersedia membeli harga lebih tinggi.
Tujuh tahun belakangan, usaha air galon menjamur di Kota Samarinda. Meski tak ada yang menjamin aman atau tidaknya kualitas air dari bisnis individu dan CV ini, tapi air galon disukai karena bisa langsung diminum. Dalam satu bulan, sebuah rumah tangga terdiri 5-6 orang membutuhkan sekitar 15 air galon, pengeluarannya sekitar Rp240 ribu. Jika angka ini digabung dengan biaya pembelian air tangki yang mencapai 4 kali sebulan, total kebutuhan air bersih antara Rp560 ribu dan Rp1.040.000. Angka ini setara 19-36% upah minimum Kota Samarinda
Di musim hujan, krisis air terjadi karena banjir. Resapan air yang hilang dan drainase yang buruk berakibat sungai-sungai melimpah, banjir membawa air kotor bercampur sedimen. Sejak 15 tahun terakhir, banjir menjadi langganan penduduk kota.
Pada November 2008 hingga Juni 2020, banjir meluas menggenangi hampir setiap sudut kota. Sekitar 50.000 jiwa terdampak banjir. Dalam setahun sedikitnya 5-6 kali terjadi banjir besar, menenggelamkan jalan-jalan utama dan menghentikan aktivitas perekonomian warga, termasuk transportasi umum dan pasar, memengaruhi lapangan kerja dan pendapatan penduduk.
Memulihkan Ruang Hidup Bersama, Mungkinkah?
Tentu Kota Samarinda tak melulu tentang cerita krisis. Warga kota aktif melawan kondisi itu dan berupaya melakukan pemulihan.
Anak-anak muda yang tergabung dalam organisasi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur mengingatkan mengenai krisis air. Mereka menyerukan pertambangan batubara harus segera dihentikan agar Samarinda mampu mengatasi krisis sosial-ekologis. Pada 2011, Gerakan Samarinda Menggugat dan JATAM memfasilitasi gugatan citizen lawsuit pertama di Asia Tenggara yang mengkaitkan batubara, banjir, dan perubahan iklim serta matinya anak-anak di lubang tambang. Selama tiga tahun proses pengadilan, gugatan membangkitkan kesadaran dan menggalang dukungan berbagai kelas dan kelompok warga kota, termasuk petani, akademisi, mahasiswa, agamawan, termasuk LGBT.
Pada 2014, gugatan warga itu menang di Pengadilan Negeri Samarinda. Kemenangan berikutnya pada 2016 saat pengadilan menolak banding para pejabat pemerintahan daerah dan nasonal.
Hakim menyatakan pemerintah daerah dan nasional, yang mengabaikan pengawasan terhadap izin tambang, merupakan “perbuatan melawan hukum.” Pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Para hakim di MA, sayangnya, menggagalkan gugatan warga dengan alasan sistem peradilan Indonesia tidak mengenalnya. Keputusan lembaga hukum tertinggi di negara ini merugikan warga Samarinda.
Pada 2016, sekelompok aktivis lingkungan membentuk komunitas pecinta sungai dan mendirikan Sekolah Sungai Karang Mumus. Mereka melakukan pendidikan dan menggalang gotong royong warga agar peduli pada sungai Karang Mumus jika ingin mendapat pasokan air bersih dan sehat. Mereka memungut sampah secara rutin di tepian sungai. Dalam tiga tahun terakhir warga berhasil menanam lebih dari 9 ribu pohon di sepanjang sungai.
Memulihkan the commons atau ruang hidup bersama tentu bukan perkara mudah. Warga kota harus bersatu dan merebut dukungan politik, mereklaim dan menata ruang penghidupan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kompleksitas persoalan kota yang membentuk karakter pemangsaan (predatory) ini harus dijadikan latar untuk mengubah kota menuju cita-cita pemulihan dan penataan ruang hidup di masa depan.
Warga Kota Samarinda penting memiliki kesadaran sejarah ruang hidup yang telah diprivatisasi berlapis (multiple privatisation) sejak masa kolonial, yang membuat mereka menjadi “pengungsi” di ruang-ruang kota yang tersisa (residual spaces). Kita telah lama tinggal di lingkungan yang terus memburuk. Kita dipaksa menyesuaikan arahan-arahan pengurus negara dan seluruh kualitas kehidupan kita dipaksa menopang permintaan komoditas pasar global.
Ini menuntut perubahan pandangan seluruh warga termasuk imajinasi tentang masa depan, membayangkan masa transisi seperti apa hidup berdampingan dengan sungai, sebagai the commons. Thus, cita-cita mulia pasal 5 UU No.7/2004—bahwa setiap orang bisa mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif—bukanlah mustahil. Model-model pengurusan bersama seperti Komunitas Sekolah Sungai Karang Mumus di Samarinda perlu diperbanyak dan diperluas sehingga menjadi inspirasi merebut kembali the commons.
Maka, model pembangunan kota yang berkarakter pemangsaan (predatory) harus diubah menjadi pembangunan kota yang merawat kemanusiaan dan alam.
========
*Tulisan ini telah dimuat di media daring tirto.id pada 5 Juni 2020 dengan judul sama persis yang tercantum. Sumber tulisan bisa dikunjungi di sini.
Siti Maimunah adalah peneliti Sajogyo Institute, mahasiswa Universitas Passau, WEGO-ITN Marie Sklodowska-Curie Fellow, pendiri Tim Kerja Perempuan dan Tambang
Sarah Agustiorini adalah aktivis dan peneliti Tim Kerja Perempuan dan Tambang