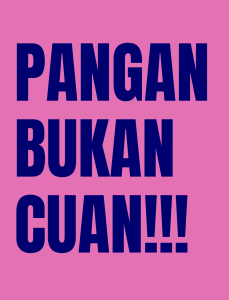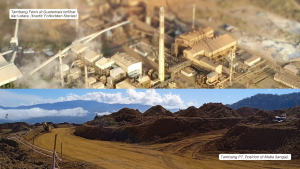Belakangan ini kita disuguhi potret pilu kekerasan berbasis konflik agraria terhadap masyarakat petani miskin pedesaan oleh suatu kolaborasi ‘tangan-tangan’ pemilik modal (perkebunan, kehutanan dan tambang) dan negara (beserta aparatus keamanannya) yang kembali semarak muncul, misalnya, kekerasan atas ibu-ibu petani oleh Semen Indonesia di Rembang (Jateng) dan kriminalisasi 3 petani/nelayan miskin di Ujung Kulon Banten, masyarakat pedesaan di Kupang, Bima, Makasar, Nenek Asiyani di Situbondo (Jatim) dan seterusnya.
Kekerasan dan konflik tersebut tentu saja pucuk gunung es dari beragam masalah sejenis yang tidak/belum terekspos media secara nasional. Laporan kekerasan dan konflik agraria yang dikeluarkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada 2013 menyebut, terdapat 369 kasus konflik agraria di seluruh Indonesia selama 2013 atau terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan pada 2011 dan 2011 (198 dan 108 kasus konflik). Selama SBY memimpin (2004-2013) terjadi sebanyak 987 kasus,–hanya 21 petani/warga tewas, 30 orang tertembak, 130 orang dianiaya dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan yang dapat dijangkau dan dilaporkan ke KPA. Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 139.874 kepala keluarga, sementara luas areal konflik mencapai 1.281.660.09 ha (meningkat tajam, sebelumnya 2012: 318.248, 9 ha). Dari 987 kasus yang terjadi, 180 di sektor perkebunan, 105 kasus di sektor infrastruktur, pertambangan 38 kasus, 31 kehutanan, pesisir kelautan 9, lain-lain 6 kasus.
Seiring dengan ini, laporan dari Komnas HAM RI tahun 2013 menunjukkan bahwa laporan yang masuk lebih pada persoalan konflik agraria dan sumber daya alam. Setiap tahun tak kurang 6000 kasus yang masuk ke Komnas HAM, dan lebih dari separuhnya adalah kasus berbasis tanah dan sumber daya alam (SDA). Ini pun yang resmi terlaporkan. Atas dasar inilah, dan juga dalam rangka mendorong implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, pada tahun 2013-2014 ini melakukan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak Masyararakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”. Kasus yang diselidiki secara menyeluruh adalah di 7 region (Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Bali Nusra, Papua).
Dari 40 kasus yang terpilih, menunjukkan pelanggaran HAM berat, sistematis dan kronis atas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan Hutan. Temuan awal dari Inkuiri Nasional Komnas Ham ini menunjukkan kejahatan, kekerasan, kriminalisasi, diskriminasi dan pelanggran berat HAM masih terjadi melibatkan pihak Keamanan Polri (Paling dominan kesatuan Brimob) dan TNI Angkatan Darat, Perusahaan (negara dan swasta) : Tambang (Emas, Batubara, Nikel), Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, PTPN), Kehutanan (Konservasi, Hutan Lindung, HTI), juga melibatkan pihak Pemernitah Pusat dan Daerah serta masyarakat (kelembagan adat bentukan pemerintah).
Sumber utama konflik adalah pemberian konsesi dan ijin kepada pihak-pihak pengusaha (pemilik modal; dalam dan luar negeri) baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mengabaikan hak MHA di kawasan hutan dan dilibatkannya militer ( TNI dan Polri) sebagai pengaman bagi perusahaan dan hak konsesi mereka. Bahkan di beberapa kasus, TNI dan Polri adalah bagian dari pelaku bisnis dan pengelola dari konsesi tersebut (pertambangan, kehutanan, perkebunan). Laporan keseluruhan dalam proses penulisan untuk menjadi rekomendasi nasional yang akan diberikan kepada Presiden paling lambat awal tahun depan.
Ketimpangan Struktur Agraria dan Globalisasi
Sayangnya, masalah kekerasan atas petani miskin pedesaan ini lebih banyak dipersepsikan pada sudut pandang ‘sektoralisme-tematik’; HAM, keamanan, masyarakat adat, pengalihan isu politik nasional, dan pelanggaran-pelanggaran hukum negara lainnya. Persepsi ini cenderung membias dari akar masalahnya, yakni ketimpangan penguasaan, pemilikan,dan peruntukan sumber-sumber agraria nasional. Satu bentuk ketimpangan struktural agraria yang nyata-nyata mengingkari mandat konstitusional baik UUD 1945 (khususnya Pasal 33), UUPA 1960, TAP MPR No IX/2001, maupun Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang mengatur pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pada praktiknya, kekayaan alam, aset nasional, dan sumber penghidupan rakyat hanya dimiliki oleh segelintir penguasa modal (baik pribumi maupun asing). Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2010), kurang lebih 56% aset nasional dikuasai hanya 0,2% dari penduduk Indonesia. Dengan kenyataan semacam ini, dapat dikatakan bahwa para petani pedesaan sudah kehilangan jaminan tenurial security atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam.
Hampir seluruh kebijakan dan program pembangunan negara hari ini sulit dijelaskan secara terang benderang tanpa mengaitkannya dengan kepentingan politik-ekonomi dari kapitalisme global. Pemberian konsesi dan hak penguasaan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan, pulau-pulau kecil, dan beragam sumber agraria lainnya kepada pengusaha-konglomerat pribumi maupun Trans National Corporation (TNC) adalah bagian nyata dari kolaborasi dan kaitkelindan kepentingan ekonomi-politik guna akumulasi modal sebesar-besarnya untuk lembaga dan kelompok oligarkis mereka sendiri.
Untuk tujuan itu, beragam pintu masuk dan “karpet merah” masuknya modal diperlebar, apa yang dianggap menyumbat“ leher botol” investasi ditiadakan. Maka tak heran jika lahir beragam regulasi sektoral pasca reformasi yang lebih pro pemodal raksasa dan mengabaikan hak masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 18/2003 tentang Perkebunan, Undang-Undang No 7/2004 Sumber Daya Air, UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU Holtikultura, UU Lahan Abadi Pertanian,UU Migas,dan yang terbaru adalah UU Pengadaan Tanah yang baru disahkan pada Desember 2011. Sementara ‘payung’ hukum pengelolaan sumber- sumber agraria nasional yang dimandatkan UUPA tahun 1960 tidak kunjung dihidup-tegakkan. Dengan melihat kaitkelindan hubungan integral negara dan kapitalisme, dapat dipahami segala hal yang dianggap menghambat jalan utama sirkuit modal akan ditiadakan (kalau perlu) dengan cara apa pun.
Masyarakat petani pedesaan yang hidup di sekitar/dalam kawasan perkebunan, pertambangan hutan, dan sumber-sumber agraria lainnya (yang kerap) dianggap sebagai masalah dan ancaman akan menjadi bagian yang akan disingkirkan paksa. Jika masih dan mau ditundukkan, mereka akan menjadi cadangan buruh murah, tentu setelah mereka terputus hubungan dengan aset tanah dan alam mereka. Proses terlemparnya petani pedesaan dari hubungan-hubungan tradisionalnya dengan tanah dan alam menjadikan mereka hanya berpangku pada tenaga dirinya sendiri. Sementara untuk berkompetisi di wilayah industrialisasi perkotaan, mereka tak cukup keterampilan dan pengetahuan. Barangkali di tengah “ketiadaan pilihan” itu apa pun akan mereka lakukan, sekadar untuk bisa bertahan hidup, mempertahankan basis subsitensi mereka yang makin terancam. Meski harus jahit mulut, harus dipukuli, dipenjara, dibacok,dan tertembak mati.
Dalam karya klasiknya The Great Transformation, Karl Polanyi (1944) sudah menegaskan bahwa “tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah”.
Nalar Elit Negara
Problem konflik agraria di atas beririsan kuat dengan nalar elit Negara mengatur rakyat dan sumberdaya alamnya. Problem mendasar kebijakan politik negara yang sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi terus berulang adalah apa yang disebut oleh W.F Weritheim (2009) watak “sociology of ignorance” (sosiologi kemasa-bodohan/pengabaian). Beragam kebijakanan dan program politik negara seringkali lebih banyak di susun di atas meja dan oleh segelitir orang, yang berada jauh dan mengabaikan realitas empirik sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kacamata ini, persepsi kaum elit lebih didonimasi oleh “false conciousness” (kesadaran palsu) tentang persepsi massa kaum miskin. Sebab segala kalkulasi dan indikator kemiskinan lebih berdasar pada angka-angka dan perpsektif makro ekonomi semata. Aspek ketimpangan struktur penguasaan lahan, dampak kerusakan dan krisis sosial-ekologis, konsentrasi aset sumber daya alam dan agraria, persoalan asimetri informasi pasar dan sejenisnya tidak menjadi pertimbangan, atau sengaja diabaikan. Akibatnya, lahirlah bentuk-bentuk politics of ignorance. Sebuah perilaku dan sikap politik pengabaian, ketidaktahuan dan ‘masa bodoh’ atas suara lapis bawah atau persepsi massa. Gap persepsi elit negara dan persepsi massa ini sangat terasa melingkupi persoalan kebangsaan dan kenusantaraan kita hari ini. Tak heran, jika penyelesaian beragam krisis sosial-ekologis, konflik agraria yang kronis (sebagimana dijelaskan di awal), krisis energy, kemiskinan dan beragam ketimpangan struktur agrarian lainnya lebih pada tujuan ‘lip service, charity, reaktif dan karikatif’ daripada mencari solusi pada akar masalah kemiskinan (dan juga konflik) yang sebenarnya.
Kemiskinan Struktural-Relasional
Nalar elit negara dan wakil rakyat yang berwatak politics of ignorance telah meletakkan problem kemiskinan semata sebagai “kondisi”, bukan sebagai “konsekuensi”. Kemiskinan sebagai kondisi, melahirkan cara penanganan masalah kemiskinan yang lebih economic minded yang melahirkan terjemahan tingkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi. Padahal kemiskinan yang terjadi di negeri ini lebih sebagai ‘konsekuensi’. Sehingga kemiskinan harus dililihat pada beragam kompleksitas ketimpangan hubungan sosial-ekonomi-politik secara “historis dan struktural” dalam rentang panjang yang terus berulang dan mencipta serta mengakibatkan beragam kemiskinan yang terwariskan. Dengan cara pandang ini menurut David Mosse (2007) kemiskinan adalah bersifat relasional. Hasil bentukan dari relasi kekuasaan (sosial-ekonomi-politik) yang timpang yang bersifat historis dan struktural. Sehingga, mengatasi kemiskinan berwatak relasional tidak akan tuntas jika mengabaikan penyebab ketimpangan relasi kekuasaan yang menyebabkannya.
Menurut pandangan Sajogyo dan “Madzhab Bogor” lainnya, sebagaimana dikutip Wahono (2011), persoalan kemiskinan dan ketimpangan relasional harus dikaitkan dengan persolan ketimpangan struktur agraria. Kuncinya adalah pada penguasaan sarana-sarana produksi keagrariaan, yang meliputi tanah, air, keanekaragaman hayati, udara dan sebagainya. Dengan dasar ini, apapun positifnya intervensi negara maupun swasta dan swadaya rakyat dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, jika penguasaan sarana-sarana produksi masih timpang, akhirnya tetap saja tidak akan membawa kepada penyelesaian sejati, atau bahkan memperparah ketidakadilan sosial.
Oleh karena itu wacana tentang keadilan, pertanian, dan pembangunan, pokok kunci persoalannya selalu kembali pada siapa yang menguasai sarana produksi, berapa dan bagaimana, serta untuk atau dinikmati oleh siapa. Dengan pandangan berwatak “sosialisme kerakyatan” semacam ini, maka setiap kebijakan pengurangan kemiskinan atau peningkatan kemakmuran rakyat harus selalu mempertimbangkan keadilan sarana produksi, dan mampu membumi dalam sebuah penyelesaian sederhana namun kunci. Gagasan Sajogyo tentang pengorganisasian tata produksi lahan terbatas oleh petani gurem dan buruh tani yang tersimpul pada konsep Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) dan konsep “Dalapan Jalur Pemerataan” penting untuk dikontekstualisasikan kembali. Sayang, pemerintah belum sungguh-sungguh menerapkannya hingga kini.
Maka, “wajar” jika watak nalar elit Negara dan wakil rakyat yang masih mengidap politics of ignorance itu meletakkan persoalan penundaan harga BBM dan rencana Bantuan Langsung Sementara (BLS) dianggap sebagai “solusi” mengatasi atau mengantisipasi kemiskinan. Padahal jenis kemiskinan yang dialami masyarakat bukan sekedar “kondisi”, tetapi lebih sebgai “konsekuensi” yang bersifat relasional. Dan menjadi wajar pula, jika masyarakat dan mahasiswa tetap tidak terima argument “penundaan” harga BBM itu, bukan karena tidak faham hitungan-hitungan rasionalisme politik ekonomi para elitnya, tetapi lebih karena pemerintah dan wakil rakyat nampak seolah tidak peka dan masa bodoh (ignorance) pada persoalan empirik mereka keseharian dan penantian panjang perubahan nasib mereka untuk “keadilan sosial bagi seluruh Indonesia” yang menurut Buya Syafi’I Maarif telah lama diyatim-piatukan negara. Sebab diatas semua tujuan kebijakan pembangunan demi dan untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan tidak otomatis selaras dengan prinsip dan nilai keadilan sosial.
Dari sekilas uraian di atas dapat dikatakan bahwa beragam ketimpangan struktur agraria adalah akar dari semaraknya masalah konflik agraria dan terciptanya bentuk-bentuk kemiskinan struktural-relasional yang merupakan ujung dan akibat dari kuatnya gurita sistem kapitalisme bekerja dalam ragam banyak bentuknya yang berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lainnya.
Wallahu ‘alam bissowab