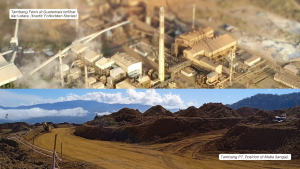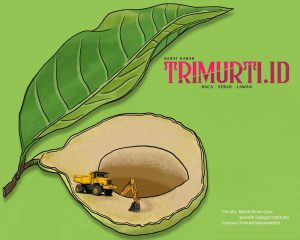Harian Kompas telah mengoyak empat isu strategis terkait desa dalam sebulan terakhir.
Pertama, penguasaan lahan di desa sudah tidak dalam genggaman warga desa, tetapi dikuasai pemodal kakap di luar desa (kota). Kedua, desa telah menjadi pasar barang/jasa yang mengalir dari kota (juga komoditas impor) sehingga mekanisme pengisapan ekonomi terus terjadi. Ketiga, rantai distribusi/logistik yang amat panjang dianggap pemicu tingginya harga pangan, sehingga koperasi dan/atau badan usaha milik desa (BUMDes) diharapkan punya daya memperpendek rantai tersebut agar inflasi pangan bisa dikendalikan. Keempat, rasio gini di desa turun drastis setahun terakhir ini dari 0,32 (September 2014) menjadi 0,27 (September 2015).
Sebagian menduga penurunan ini karena terjadi pemiskinan massal sehingga yang berlangsung di desa adalah “pemerataan kemiskinan”. Sebetulnya keempat isu itu saling bertautan dan punya daya pukul mematikan jika tak diurus sejak sekarang.
Penguasaan sumber daya
Belakangan ini teori ekonomi yang mengupas soal faktor produksi digeser pemaknaannya dengan menyatakan tak penting siapa yang memilikinya. Bahkan, bila dikuasai pelaku ekonomi asingpun juga tak masalah, sepanjang bisa menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang/jasa, dan seterusnya.
Faktanya, penguasaan faktor produksi tersebut, khususnya lahan dan modal, menjadi jangkar paling dalam bagi penciptaan ketimpangan (pendapatan) yang akut. Ragam kebijakan yang diluncurkan untuk mengatasi ketimpangan tak bertenaga karena tak menyentuh perkara penguasaan sumber daya itu. Bahkan, ketimpangan dalam 10 tahun terakhir melaju cepat seiring dengan pemburukan pemerataan distribusi sumber daya ekonomi.
Oleh karena itu, penguasaan sumber daya di tangan kaum tunalahan atau tunamodal merupakan agenda serius yang mesti diperjuangkan. Kenyataan inilah yang enggan dijangkau sehingga dengan kepastian yang tinggi tanah di desa sudah berpindah tangan dan dikuasai sekelompok tuan tanah (baru).
Jika kemudian penguasaan lahan di desa (juga sumber daya ekonomi lainnya) tak lagi di tangan warga desa (petani), maka hal itu tidaklah mengejutkan karena prosesnya dibiarkan terus terjadi, bahkan difasilitasi. Ini berbeda sekali dengan konstruksi para pendiri bangsa yang mendesain Pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian diwujudkan dalam semangat kolektivitas dan tidak dibiarkan sumber daya dikuasai oleh orang per orang dalam jumlah yang sangat besar.
Hal itu dipertegas dengan hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 5 Tahun 1960, yang memberi makna “sosial” terhadap sumber daya tanah. Oleh karena itu, distribusi penguasaan tanah tak boleh dibiarkan semata karena kalkulasi ekonomi dengan menumpang mekanisme pasar, tetapi harus lebih banyak menafkahi aspek sosial (keadilan). Problem inilah yang terjadi saat ini, di mana Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA tak lagi dijadikan sandaran dalam mendesain konsepsi hak kepemilikan dan alokasi penguasaan lahan (tanah).
Harapan kembali mengalir ketika program reforma agraria yang digelindingkan saat ini hendak dijadikan satu paket dengan pembangunan desa. Penguasaan lahan di desa harus dihentikan dan didistribusikan demi menyemai daya hidup warga desa. Politik fiskal yang memberikan desa anggaran dalam jumlah memadai dan terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan syarat perlu, akan tetapi tak mencukupi.
Pada posisi ini, reforma agraria adalah bagian dari syarat cukup (di luar kebijakan keuangan, pertanian, perdagangan, industri, dan lain-lain). Pilihan reforma agraria bukan hanya mendistribusikan lahan yang menganggur atau dikuasai oleh negara (seperti Perhutani), tetapi juga memangkas korporasi swasta yang telah membekap gurita lahan dan sumber daya alam lainnya. Pada level tertentu, dengan bekal UU Desa (UU No 6/2014), desa bahkan memiliki otoritas melakukan reforma agraria skala lokal dan penguasaan lahan bagi kemaslahatan bersama.
Desa dan pasar
Desa sebagai pasar tentu saja realitas yang tak bisa ditolak. Dalam pengertian tertentu, desa adalah pasar yang besar karena sebagian besar penduduk saat ini masih tinggal di desa, meski dengan proporsi jumlah yang kian mengecil dengan daya beli yang rendah. Meski demikian, nasib paling nahas yang dihadapi desa sekarang adalah tertikam oleh pasar yang dinyatakan dalam abstraksi: “produsen barang primer dan konsumen barang sekunder/tersier”.
Jadi, produsen komoditas primer bukanlah hal buruk karena hal itu bagian dari matra aktivitas ekonomi yang penting. Menjadi persoalan bila komoditas primer itu dijual keluar (kota) untuk diolah kembali dengan nilai tambah yang besar dan dijual balik ke desa. Situasi yang mudah ditebak dari kisah itu adalah penyedotan ekonomi secara sistematis, sehingga hasil penjualan tak cukup untuk mengongkosi kebutuhan hidup. Bahkan, pada produk primer sekalipun banyak petani sudah menjadi konsumen.
Dua isu berikut telah digelindingkan dan hendak dikonversi jadi kebijakan. Pertama, penguasaan dan kepemilikan sumber daya di desa mesti digandakan jadi kegiatan yang mempunyai nilai tambah, yang sering disebut “industrialisasi desa”.
Istilah ini tidak salah, tetapi imajinasi atas model industrialisasi perlu dipetakan dengan baik. Industrialiasi yang memiliki arti transformasi ke aktivitas ekonomi modern dengan induksi modal, teknologi, dan inovasi tak boleh dibiarkan berlalu di atas hamparan kepadatan modal yang berlebih ataupun injeksi teknologi yang asing bagi warga desa.
Perlu dipahami, industrialisasi di sini dimaknai sebagai ikhtiar memuliakan sumber daya ekonomi di desa lewat modal yang ditanggung secara kolektif, memasukkan sebagian besar pelaku ke tengah arena, dan mengerjakan secara bersama. Bila ini yang dijalankan, tidak akan terjadi sebagian (kecil) pelaku ekonomi membajak hasil pembangunan untuk kaumnya sendiri.
Kedua, pasar tak boleh dilepaskan dari aturan main yang di- kendalikan oleh desa. Komoditas yang sudah memiliki nilai tambah tersebut selain berfungsi memproteksi sumber daya agar tidak keluar dari desa terlebih dulu, juga memastikan komoditas yang diproduksi dalam kendali mereka dalam distribusinya. Bahkan, distribusi tersebut juga termasuk dalam komoditas yang hendak masuk ke desa.
Banjir komoditas ke desa harus dimaknai sebagai penetrasi barang/jasa yang bukan merupakan kebutuhan, tetapi sebagian besar daftar “keinginan” yang dilesakkan lewat media iklan secara masif. Demikian pula pelaku distribusi itu tidak dalam cengkeraman warga desa sehingga nilai tambah mata rantai tata niaga juga lepas dari mereka. Aturan main ini mesti dibuat secara mikro (level desa/komunitas) dan makro (pemerintah pusat/daerah), khususnya kebijakan perdagangan. Kementerian atau dinas perdagangan jadi titik tumpu regulasi pada level makro.
Lumbung ekonomi desa
Sampai titik ini, agenda penguatan organisasi ekonomi yang kukuh di desa menjadi amat vital. Koperasi merupakan tulang punggung untuk menyulut energi atas kelemahan pelaku ekonomi di desa. Spirit kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong menjadi akar dari gerakan ekonomi ini.
Di masa lalu, sebelum digerus oleh aneka penyimpangan nilai, koperasi jadi penyangga harkat hidup warga desa. Sekarangpun masih banyak koperasi yang berjalan sesuai khitah, sehingga fungsinya berjalan dengan rapi di masyarakat. Di luar itu, UU Desa juga memberikan mandat membentuk BUMDes sebagai penyangga perekonomian desa. BUMDes digagas untuk mengelola sumber daya ekonomi, sekaligus memperkuat watak kolektivitas yang berakar kuat di desa. Sungguhpun begitu, operasi BUMDes tak boleh bertubrukan dengan aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan rakyat selama puluhan tahun. Keberadaannya justru harus berpadu dan memperkuat ekonomi rakyat.
Pada konteks desa, dua jalur yang relevan dimasuki oleh BUMDes. Pertama, jadi perekat atas titik kegiatan ekonomi yang telah dijalankan rakyat secara mandiri. Mereka biasanya dikendalai dengan permodalan, bahan baku yang murah, dan distribusi yang lemah. BUMDes memasuki wilayah tersebut, sehingga posisi tawar dan efisiensi aktivitas ekonomi rakyat menjadi lebih bagus. Ini sekaligus menjadi jawaban atas inefisiensi rantai distribusi yang membuat desa selalu memperoleh nisbah ekonomi yang kecil dan konsumen harus membeli dengan harga mahal.
Kedua, BUMDes beroperasi menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 sehingga hanya masuk ke cabang produksi penting dan atau terkait sumber daya alam. Beberapa BUMDes sudah berjalan dengan, misalnya, mengelola sumber daya air yang dikonversi untuk tujuan ekonomi, sebagian lagi murni kepentingan pelayanan publik (menyalurkan air bersih untuk warga desa).
Jika cara-cara semacam itu hidup dan langgeng di desa, maka tak usah cemas dengan paradoks pertumbuhan dan ketimpangan, seperti yang terjadi di kota saat ini. Pola dominasi penguasaan dan kepemilikan (juga ekonomi yang sangat padat modal dan teknologi) di kota telah menjadi sumber peningkatan ketimpangan (pendapatan). Desa harus dijadikan pulau yang kalis dari praktik tersebut.
Jika saat ini ketimpangan pendapatan di desa telah menurun sangat drastis, maka itu harus disambut dengan sukacita, sambil memeriksa kemungkinan terjadinya pemerataan kemiskinan. Jika kemungkinan terburuk itu yang terjadi, tetap saja peluang terbuka lebih lebar untuk memperbaiki di masa depan karena telah tumbuh politik fiskal yang berpihak pada desa (dana desa dan alokasi dana desa). Jika itu diperkaya dengan penguatan ekonomi yang bernilai tambah, pasar yang dikontrol secara efektif, penguasaan sumber daya, dan organisasi/lembaga ekonomi yang mapan, maka lumbung ekonomi desa akan terbangun dan kesejahteraan warga desa akan segera turun dari langit.
Ahmad Erani Yustika
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Opini ini sebelumnya telah diterbitkan di Kompas pada tanggal 18 Februari 2016