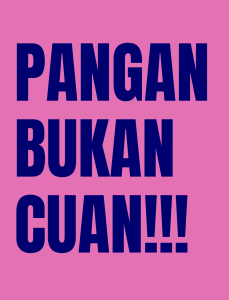Setelah setahun lebih angkat senjata, pada 29 Desember 2015 Din Minimi dan puluhan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyerahkan diri. Hal ini mengkhiri perlawanan mereka yang, uniknya, ditujukan kepada Pemerintah Aceh ketimbang Pemerintah Pusat. Sejak itu perdebatan yang terus mencuat adalah seputar berhak-tidaknya kelompok ini memperoleh amnesti. Padahal, pemberian amnesti hanyalah penyelesaian atas status hukum kelompok ini, bukan atas akar masalah yang mendasari perlawanan mereka. Akar masalah itu sendiri terletak pada ketegangan sosial-politik terkait reintegrasi dan transformasi eks kombatan. Seharusnya hal terakhir ini mendapat perhatian yang lebih besar agar siklus kekerasan tidak terjadi di Aceh.
Awalnya Kekecewaan Ekonomi
Tindakan kelompok Din Minimi mengangkat senjata semula didorong oleh kekecewaan ekonomi atas kegagalan program reintegrasi menyediakan rumah, lahan pertanian dan pekerjaan kepada eks kombatan dan korban konflik. Di sisi lain, mereka disuguhi kemewahan hidup para pemimpin dan rekan mereka yang memiliki akses kekuasaan. Karena itu, saat mendeklarasikan gerakannya pada 9 Oktober 2014, Din Minimi menegaskan bahwa pihaknya mengangkat senjata bukan untuk memusuhi aparat keamanan, melainkan “melawan pemerintah [Aceh] yang hanya memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rakyatnya.”
Gubernur Zaini bereaksi keras terhadap aksi perlawanan ini. Alih-alih membuka dialog, pemenang pilkada 2012 yang penuh kekerasan ini meminta aparat keamanan bertindak tegas. Hal ini diaminkan oleh Polda Aceh yang segera menggelar operasi represif. Di tengah kejaran pihak Polri, pada 23 Maret 2015 kelompok Din Minimi membunuh dua staf intelijen TNI. Anehnya, insiden ini justru membuat TNI gencar melakukan persuasi. Danrem Liliwangsa mengunjungi rumah orang tua Din Minimi, sementara Pangdam Iskandar Muda menelpon Din Minimi dan membujuknya turun gunung. Aroma persaingan di antara TNI dan Polri tidak bisa ditutupi lagi.
Pada tahap ini, persoalan telah kian pelik. Lembaga kajian IPAC pimpinan Sidney Jones melaporkan, pada akhir Desember 2014 Din Minimi dihubungi “Ayah Oh”, perantauan Aceh di Norwegia yang merupakan aktivis ASNLF—lembaga sempalan GAM yang menolak perdamaian Helsinki 2005. Selain membicarakan donasi pembelian senjata, entah kesepakatan apa lagi yang mereka buat. Laporan itu juga menyebut kontak Din Minimi dengan Tgk. Mukhtar, sosok di balik kasus kamp militer untuk pelatihan teroris di Jantho, Aceh Besar.
Aksi kelompok Din Minimi pada perkembangannya telah menarik banyak pihak untuk “mengail di air keruh”. Hal ini meningkatkan posisi tawar dan makna simbolik gerakan ini, dan memungkinkan pendefinisian ulang tuntutan-tuntutan mereka. Begitulah, kelompok ini berhasil menaikkan level pertaruhannya saat menegosiasikan penyerahan diri mereka. Selain tuntutan awal penuntasan program reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi, mereka menuntut sejumlah persyaratan lain yang memiliki bobot politik yang kental, seperti pemberian amnesti, pengusutan korupsi di Aceh oleh KPK, dan pengerahan pemantau independen pada pilkada 2017. Kasus Din Minimi tidak lagi sebatas kekecewaan ekonomi!
Preseden Sejarah
Kasus Din Minimi bukanlah gerakan perlawanan pasca-konflik yang pertama di Aceh. Ia memiliki preseden jauh lebih awal, yakni pada gerakan Sayid Ali Assegaf. Gerakan ini terjadi pada Maret 1948, tepat dua tahun usai Perang Cumbok dan rangkaian revolusi sosial yang menyertainya (Januari-Maret 1946).
Seperti diketahui, revolusi sosial 1946 ini berhasil menumbangkan kekuasaan uleebalang dan menobatkan para tokoh ulama modernis dan pemuda Pesindo pada tampuk kepemimpinan, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun militer. Dengan demikian, lahirlah rezim PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di Aceh. Namun belum lama memerintah, elit penguasa baru ini segera diterpa badai kecaman dan perlawanan.
Dalam konteks Aceh, kejatuhan elit lama ternyata segera disusul oleh deligitimasi elit baru. Hal ini terjadi dalam tempo cukup pendek dan penuh kekerasan. Begitulah, ketegangan internal dalam struktur sosial Aceh yang memuncak pada revolusi sosial 1946 telah melahirkan ekses-ekses negatif, seperti penahanan dan pembunuhan di luar proses hukum (bahkan hingga jauh seusai revolusi sosial), proses penyelesaian harta benda rampasan yang partisan, dsb. Pada saat yang sama, gairah revolusi telah memupus peluang untuk rekonsiliasi dan pengungkapan sejarah. Situasi inilah yang dua tahun kemudian memicu gerakan Sayyid Ali yang menggoyang rezim PUSA, meski akhirnya dapat dipatahkan Tgk. Daud Beureueh yang menjabat Gubernur Militer. Para pemimpin gerakan ini ditangkap dan dipenjarakan hanya sehari sebelum aksi massa dilaksanakan pada 4 November 1948.
Pada 21 Desember 1949, abolisi umum diberikan oleh Pemerintah Pusat, baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam revolusi sosial 1946 maupun para uleebalang dan oposan rezim PUSA yang selama ini ditawan. Namun, tanpa ada kebijakan untuk mengatasi akar ketegangan sosial di Aceh, antagonisme di antara kedua kubu tetap membara. Hal ini segera menemukan ajang pertikaian baru, yaitu pada tarik menarik otonomi Aceh selama transisi ketatanegaraan dari RIS ke RI (1949-1950)—dengan pihak PUSA ngotot mempertahankan provinsi Aceh, sementara para penentang PUSA mendukung pembubarannya. Ajang pertikaian baru ini pada gilirannya melatari siklus kekerasan berikutnya, yaitu Pemberontakan Darul Islam pada 21 September 1953. Pemberontakan yang dipimpin Tgk. Daud Beureueh ini, dengan demikian, turut dilatari oleh ketegangan internal yang telah lama ada di antara masyarakat Aceh, di samping faktor ketegangan pusat-daerah (Ibrahimy 2001).
Pelajaran Penting
Tiga pelajaran berharga dapat dipetik dari dua kasus perlawanan terhadap pemerintah Aceh ini.
Pertama, belajar dari siklus kekerasan di Aceh pasca kolonial—revolusi sosial 1946, perlawanan Sayid Ali 1948, dan pemberontakan Darul Islam 1953—faktor ketegangan internal di tubuh masyarakat Aceh ternyata memainkan peran yang penting dalam memicu konflik baru. Demikian pula, kasus Din Minimi ini—dan sebelumnya kasus bentrokan sesama eks kombatan GAM dalam pilkada 2006 dan 2012 serta pileg 2014—juga memperlihatkan kegentingan dari ketegangan internal di Aceh pasca MoU Helsinki 2005. Akar dan dinamika ketegangan lokal ini haruslah ditangani demi menghindarkan potensi kekerasan baru yang lebih besar di masa depan.
Kedua, pergolakan pasca-konflik di Aceh juga menunjukkan bagaimana soal kekerasan politik, korupsi dan dominasi ekonomi merupakan hal sensitif yang di sekitarnya sentimen ketidakpuasan dapat dikobarkan. Gerakan Sayid Ali menentang rezim PUSA dan gerakan Din Minimi melawan rezim Zaini-Muzakir berada di pusaran sentimen ketidakpuasan ini. Hal ini membuktikan bahwa di Aceh banyak orang mau mengambil risiko paling berat sekalipun untuk menjadikan rasa ketidakadilan ini sebagai basis mobilisasi perlawanan.
Ketiga, pemberian abolisi umum pada 1949 membuktikan bahwa siklus kekerasan tidak berhasil diputus karena akar masalahnya tidak dijawab. Sama halnya, dalam kasus Din Minimi, pemberian amnesti semata juga tidak menjawab akar persoalan yang justru diangkat kelompok ini sebagai dasar perlawanan mereka. Bukankah yang mereka gugat adalah ketidakberesan (juga korupsi) dalam program reintegrasi dan distribusi tanah kepada eks kombatan dan korban konflik? Bukankan komisi penyelesaian klaim harta benda (salah satu mandat MoU Helsinki) tidak kunjung terbentuk? Bukankah kekerasan politik selama pilkada 2012 dan pileg 2014 tidak pernah diungkap (yang mendasari tuntutan kelompok ini atas kehadiran pemantau independen pada pilkada 2017 mendatang)?
Tiga pelajaran ini menunjukkan bahwa kasus Din Minimi menuntut solusi yang lebih mendasar ketimbang sekedar amnesti. Dan solusi itu untuk porsi cukup besar terletak pada penanganan akar-akar dan sejarah panjang antagonisme internal di dalam masyarakat Aceh. Termasuk, dan terutama, penyelesaian ketegangan dan proses demokratisasi di tubuh GAM sendiri.
*MOHAMAD SHOHIBUDDIN
kandidat PhD pada Universitas Amsterdam, Belanda; meneliti dinamika perdamaian di Aceh untuk topik disertasinya.
Artikel di atas diterbitkan oleh Majalah Gatra untuk edisi bulan Maret 2016