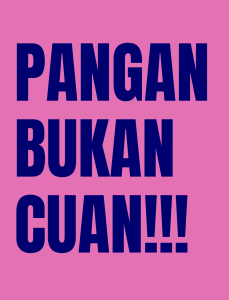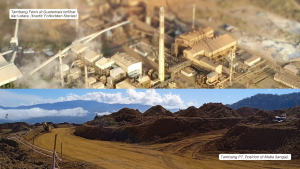Eko Cahyono
(Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Studi Center serta mahasiswa doktoral Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB University).
Beberapa pekan terakhir, kekerasan serius terjadi di beberapa wilayah. Kekerasan tersebut, antara lain, adalah pemukulan brutal aparat keamanan terhadap masyarakat Desa Pakel, Banyuwangi; misteri meninggalnya advokat anti-tambang, Jurkani, di Kalimantan Selatan; kekerasan terhadap masyarakat yang menolak penambangan untuk pembangunan bendungan Wadas, Purworejo; kriminalisasi terhadap Kepala Desa Kinipan, Wilem Hengki, di Kalimantan Tengah; serta marginalisasi masyarakat adat Marafenfen di Kepulauan Aru, Maluku.
Kasus-kasus itu dapat menjadi contoh aktual dari puncak gunung es masalah sejenis di Nusantara. Semakin hari, rezim pembangunan tampak semakin kuat menganggap tindakan kekerasan itu sebagai hal biasa seraya menyembunyikannya dalam jargon “demi menjaga masuknya tsunami investasi serta memperlancar tujuan proyek-proyek korporasi dan proyek strategis pembangunan nasional”.
Konflik agraria serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, petani, dan rakyat perdesaan yang semakin marak dinilai sebagian pihak sebagai penanda penting dari “tidak hadirnya negara”. Benarkah? Bisa jadi sebaliknya, bahwa hal itu justru menunjukkan “sangat hadirnya negara”, tapi dengan wajah politik antagonis.
Antagonisme politik yang mewujud dalam kekerasan aparatur negara terhadap rakyat seolah-olah semakin membenarkan analisis bahwa, di era modern, kekuasaan politik telanjur dipraktikkan sebagai tindakan memimpin dan mengatur—yang ujung-ujungnya jadi menguasai dan menindas—orang lain. Sejarah menunjukkan bahwa politik selalu diselubungi oleh kategori yang anti-politik: pemaksaan, diskriminasi, dominasi, dan penyeragaman. Dalam karya klasiknya, The Origin of Totalitarianism (1973), Hannah Arendt memperlihatkan situasi sosial politik yang memungkinkan munculnya kekuasaan dan kekerasan negara yang mengandung unsur kekuasaan totaliter, sehingga suatu kehidupan politik digerakkan oleh ketidakpahaman atau prasangka tentang politik. Akibatnya, politik malah menimbulkan bencana bagi kebebasan individu dan kemanusiaan. Politik kekuasaan semakin ternodai karena kehilangan fitrah dasarnya, yakni sebagai alat kekuasaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Mengapa negara, yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, berwajah antagonis demi proyek-proyek pembangunan dan menjadi “predator” atas nasib rakyatnya sendiri? Apakah negara sebagai institusi pada dasarnya memiliki kecenderungan melakukan kekerasan?
Merujuk pada pandangan David Held dalam Political Theory and The Modern State (1989), konsep negara modern sering dikaitkan dengan gagasan tentang hukum yang bersifat impersonal dan istimewa, dengan tatanan konstitusional yang memiliki kesanggupan menyelenggarakan serta mengendalikan wilayahnya. Max Weber juga menyatakan bahwa negara adalah pemegang monopoli terhadap kekerasan yang sah. Watak dasar inilah yang menjadi induk semang dan lahan subur lahirnya kekerasan pembangunan oleh negara.
Pada dasarnya, konsepsi kekerasan pembangunan (developmental violence) (Soronsen, 1987) mengandung makna bahwa pembangunan mengandung potensi dan kecenderungan terjadinya kekerasan yang justru menghambat pembangunan. Di satu sisi, pembangunan merupakan proses menuju suatu keadaan yang lebih baik. Tapi, di sisi lain, kekerasan menjadi suatu keadaan yang bakal menghambat proses pembangunan itu sendiri.
Secara umum, kekerasan pembangunan bermula dari orientasi kebijakan pembangunan dalam arus utama pandangan kapitalis-neoliberal yang cenderung patuh melayani kepentingan kelompok berkuasa dan oligarki ekonomi politik daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Untuk tujuan itu, proses pembangunan harus dirawat dan dipelihara melalui kekuatan militer dan pendekatan keamanan, yang dalam bentuk lebih “moderat” berwujud kekerasan. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan surplus kekuatan sehingga rente ekonomi dan akumulasi kapital kelompok elite, yang disebut banyak media sebagai “kelompok 1 persen”, dapat dipertahankan. Hal ini berarti diperlukan penciptaan struktur politik yang lebih koersif. Dalam kondisi demikian, pertentangan, kontradiksi, dan konflik merupakan sesuatu yang sulit sekali dielakkan oleh rezim pembangunan yang kerap melayani tujuan pasar global.
Setidaknya ada dua analisis yang dapat menjelaskan mengapa kekerasan pembangunan itu tetap dilestarikan. Pertama, kekerasan merupakan satu dari sekian cara individu, kelompok, ataupun negara memaksakan kehendak mereka kepada orang lain. Titik tolak pemahaman kekerasan, menurut Clausewitz, adalah pemaksaan kehendak dan tentu saja bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara (Giddens, 2009).
Kedua, kekerasan diterapkan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan publik dengan dasar pertimbangan ataupun atas nama berbagai tujuan serta kepentingan. Di sejumlah negara di Asia, termasuk di Indonesia, hal ini juga dipakai untuk alasan “demi pembangunan”. Meski demikian, tindakan ini sebenarnya merupakan suatu upaya untuk membentengi penguasa dari berbagai kritik, oposisi, dan kontrol dari rakyat. Kekerasan negara dalam kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan menyelinap melalui apa yang disebut “untuk kepentingan negara”. Doktrin demikian kebanyakan diterapkan di berbagai negara yang memiliki sifat otoriter (ELSAM, 1999). Hal ini semakin mengkonfirmasi bahwa negara yang semakin sering melakukan kekerasan lebih banyak merupakan negara yang dianggap totaliter dan otoriter, yang secara umum dicirikan dengan monopoli terhadap kekuasaan, media massa, dan ekonomi, serta memonopoli ataupun mengontrol organisasi-organisasi rakyat dan masyarakat sipil.
Ujung dari pembenaran kekerasan dalam pembangunan akan mempersulit proses perwujudan cita-cita keadilan sosial dan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini terjadi karena kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang “dianggap mengganggu” kepentingan negara dan tujuan target pembangunan nasional diabdikan demi melindungi serta memperlancar sirkuit investasi ekonomi korporasi skala besar, yang umumnya dekat dengan kekuasaan. Hal ini berakibat pada semakin cepatnya proses akumulasi dan eksploitasi sumber-sumber agraria serta ekonomi nasional kepada kelompok “1 persen” semata. Ketimpangan dan kesenjangan bukannya semakin sempit, tapi sebaliknya, justru semakin lebar.
Pengabaian pemerintah dalam merespons berbagai tindakan kekerasan aparat keamanan negara dan perombakan ketimpangan struktur agraria dalam pembangunan nasional tampaknya bukan sekadar dualisme watak pembangunan. Ini juga cermin retak dari keberpihakan yang salah tujuan, yakni keberpihakan negara yang bertumpu pada kekuatan-kekuatan kapital dan pasar, yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya aktor yang dapat membebaskan ketertinggalan ekonomi bangsa ini dari negara-negara maju.
Untuk mencegah kekerasan pembangunan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah berikut. Pertama, koreksi atas ukuran-ukuran capaian dari tujuan pembangunan yang diklaim untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Produk domestik bruto (PDB), yang selama ini dijadikan indikator serta tolok ukur sahih kemajuan ekonomi suatu negara, telah terbukti memberi gambaran yang melenceng tentang masyarakat dan, karena itu, memberi masukan yang melenceng pula dalam mengambil kebijakan sosial-ekonomi suatu negara.
Ukuran kualitas hidup mesti dimasukkan serta melampaui konsep produksi ekonomi dan standar hidup di PDB. Konsep ini meliputi semua faktor yang mempengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini melampaui sisi materialnya. Dengan kata lain, ia mencakup semua faktor, termasuk yang tidak diperdagangkan di pasar dan tidak dihitung dalam statistik moneter, yang membuat hidup kita berharga (Stiglitz et al, 2011), termasuk dimensi kebahagiaan lahir-batin.
Kedua, memperkuat tawaran alternatif pembangunan yang minimal memiliki ciri-ciri umum berupa berorientasi pada kebutuhan, bersifat dari dalam dan tidak asing bagi masyarakat tersebut, mandiri, menghargai lingkungan, serta berdasarkan transformasi struktural (Hettne, 1983). Ketiga, mempertegas dan mengembalikan paradigma ekonomi politik yang bersemangatkan Pancasila yang berbentuk ekonomi-sosial lestari. Ini merupakan suatu konsep ekonomi politik yang menghadirkan perdamaian, rasa aman, jauh dari kekerasan, dan inklusif dalam kemajemukan warganya tanpa pandang bulu (Wahono, 2020). Hal ini sesuai dengan cita-cita demokrasi ekonomi Bung Hatta dan bapak pendiri negara lainnya yang bertujuan untuk kedaulatan rakyat.
Jika hal-hal tersebut tidak secara serius diwujudkan, sangat mungkin kekerasan atas nama pembangunan terus timbul, yang pada akhirnya memantik gerakan anti-negara. Kekerasan yang semula dengan mudah dilakukan aparat birokrasi negara dapat berubah membentuk spiral kekerasan lanjutan, yaitu perlawanan dari rakyat terhadap negara. Dom Helder Camara (2000) dan Fukuyama (1999) menjelaskan bahwa kekerasan yang diproduksi oleh sebuah rezim secara terus-menerus akan menghasilkan deposit kekerasan potensial baru sehingga kekerasan negara akan menjadi aset penting bagi korban untuk berbuat serupa. Inilah yang kemudian disebut sebagai kontinum spiral kekerasan yang sulit dihentikan.
***
Tulisan ini telah terbit dalam Koran Tempo, edisi Kamis, 20 Januari 2022