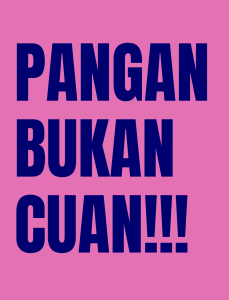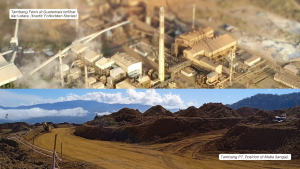Eko Cahyono
Peneliti dari Sajogyo Institute dan Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pedesaan IPB University
Melacak akar masalah agraria dan masyarakat adat hingga ke paradigma hutan ilmiah warisan pemerintah kolonial. Perlu pemenuhan syarat keamanan insani.
Salah satu akar dari ragam masalah agraria atas Masyarakat Adat di Indonesia adalah ketiadaan pengakuan legal hak dasar atas tanah-air dan ruang hidupnya. Pengabaian hak dasar ini tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang proses “teritorialisasi”. Yakni, sebuah proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktifitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu masuk ke ruang tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang aktifitas di dalam batas-batas ruang tersebut. (Vandergeest 1996).
Dalam definisi lain disebutkan bahwa teritorialisasi sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengontrol orang, fenomena, dan relasi-relasi dengan cara membatasi dan menegaskan kontrol atas suatu area geografis (Sack 1986). Dengan batasan definisi semacam ini secara spesifik hasil dari strategi teritorialisasi kontrol atas hutan dan kawasannya adalah klasifikasi semua wilayah hutan yang kemudian disebut Hutan Negara atau yang oleh para sarjana disebut sebagai “Hutan Politik” (Peluso dan Vandegeest 2001).
Secara historis tonggak-tonggak proses negaraisasi dan teritorialisasi hutan oleh negara bisa dilacak dari kebijakan politik kehutanan sejak era kolonial hingga kini. Secara ringkas, tonggak-tonggak penting kebijakan politik kehutanan tersebut dapat dalam 5 periode: secara ringkas, tonggak-tonggak penting kebijakan politik kehutanan tersebut dapat dalam 5 periode: 1) Era Kolonial Belanda (1870-1942); 2) Era Kolonial Jepang (1942-1945); 3) Era Awal Kemerdekaan (1945-1965); 4) Era Orde Baru (1965-1998); 5) Era Reformasi (1999-2014). Masing-masing periode menyumbangkan tonggak penting bagi kebijakan dan klaim negara atas kawasan hutan yang terwaris hingga sekarang.
Benang merahnya sama, hutan dan kekayaan alam yang ada di dalamnya masih dianggap sebagai komoditas dan “aset ekonomi” untuk pembangunan. Hutan masih dianggap wilayah ‘tak berpeghuni” dan kategorinya hanya dua macam: Kayu dan Non Kayu. Satu cara pandang yang melanjutkan paradigma moda produksi Kolonial abad 19 atas hutan yang sering disebut dengan Kehutanan Ilmiah (scientific forestry). Tak mengherankan, jika hal ini dianggap sebagai induk semang lahirnya benih-benih sikap anti sosial dan dehumanisasai dalam tata kelola kebijakan kehutanan (Kartodihardjo, 2016). Lahirnya konflik agraria, marginalisi, eksklusi, kriminalisasi dan pengabaian hak dasar yang menjadi bingkai masalah dasar dari masyarakat adat, perempuan dan laki-laki, dapat dilacak dari ‘warisan’ di hulu masalah tersebut.
Penjelasan akar masalah paradigmatik hutan ilmiah dalam sejarah politik kebijakan kehutanan di Indonesia ini penting ditegaskan ulang dengan menambahkan dimensi ‘ekonomi-politik’. Maka pertanyaan yang layak diajukan adalah; mengapa hutan di pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan sedikit di Jawa dengan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara melimpah, tapi kok rakyat dan masyarakat adat yang hidup disekitarnya masih banyak yang miskin dan terabaikan hak dasarnya?
Asal mula masalahnya adalah dari kepentingan kaum feudal di Eropa untuk menjaga kepentingan wilayah hutan buruannya. Maka hutan dianggap wilayah tak berpenghuni. Hutan diihilkan dari kehidupan manusia. Hutan ada untuk hutan saja.
Paradigma Kehutanan Ilmiah yang dibawa oleh Kolonial Belanda abad 19 inilah yang diadopsi untuk pengelolalan hutan di Indonesia. Untuk mewujdukan misi hutan yang bersih dari manusia ini, lalu beragam cara yang tidak manusiawi dilakukan. Salahsatunya stigmatisasi atas manusia dan kehidupannya di dalam dan sekitar/pinggiran hutan dengan istilah berkonotasi negatif, seperti perambah, perusak, penyerobot hutan, ‘pencuri’ (kayu milik negara), ‘penyabotase’ reboisasi negara, perusak ekosistem hutan, dan seterusnya (Peluso, 2006).
Tepat di titik inilah dapat dimengerti mengapa banyak kebijakan kehutanan seolah “emoh” atau bernada minor untuk tujuan pengakuan dan pemenuhan hak dasar manusia di sekitarnya, namun mudah “he-eh” dan setuju untuk tujuan korporasi dan bisnis. Akibatnya, tercipta konflik sosial-agraria dan pelanggaran HAM yang masih tinggi di sekujur wilayah Kehutanan, selain di sektor perkebunan dan pertambangan di Indonesia (KOMNAS HAM, 2016; 2019).
Angin Reformasi 1998 memungkinkan beragam prakarsa dan gerakan masyarakat sipil untuk penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak masyarakat adat di kawasan hutan semakin bergeliat muncul. Semangat reformasi juga meningkatkan ekosistem kewarasan publik dan memanggil beragam prakarsa “dari bawah” kembali bertunas. Lahirnya gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berkongres I tahun 1999 menjadi salah satu tonggak penting kesadaran pengakuan hak atas masyarakat adat secara nasional.
Gerakan AMAN dan jaringannya mengenalkan tujuan pengakuan negara (state reconition), penyelesaian konflik dan pemulihan hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai agenda sentralnya (Li, 2001; Nababan; 2018). Satu agenda yang di era sebelumnya, nampak belum menjadi agenda strategis nasional dari masyarakat sipil dan pemerintah.
Setelah melewati jalan terjal perjuangan panjang koalisi gerakan masyarakat sipil untuk pengakuan masyarakat adat akhirnya mampu membuat tonggak penting dalam perjuangan MA di Indonesia, dengan melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Sejak Putusan MK ini lahir, “Hutan Adat” bukan lagi berada di wilayah “Hutan Negara”. Maka mulai terjadi perubahan kebijakan negara untuk pemenuhan hak dasar masyarakat adat melalui kebijakan pengakuan Hutan Adat.
Kini, merujuk laporan terbaru Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per 9 Agustus 2022, terdapat 1.119 peta wilayah adat yang sudah teregistrasi dengan total luas 20,7 juta hektare, tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota. BRWA telah melakukan sertifikasi terhadap 634.216 ha di 47 peta, verifikasi 3.005.158 ha di 144 peta, registrasi 17.070.397 ha di 923 peta, dan tercatat 74.262 ha di 5 peta.
Namun demikian, proses kebijakan pengakuan Hutan Adat masih dianggap “setengah hati” oleh banyak pihak. Sebab, kebijakan pengakuan yang diberikan, masih di level pengakuan legalitas hutannya, namun belum sampai menyentuh pada pengakuan atas eksistensi identitas pengetahuan adat, termasuk pengakuan sistem tata ruang berbasis adat. Akibatnya, pengakuan tersebut dianggap belum mampu mengubah secara mendasar beragam ketimpangan struktural penguasaan sumber-sumber agraria, baik yang bersifat warisan masa lalu maupun yang sedang terjadi sekarang. Hal ini mengkuatirkan bagi kepastian jaminan keberlanjutan hak atas tanah dan kedaulatan atas sumber-sumber agaria di wilayah adat mereka (Sajogyo Institute, 2020).
Dari sisi kebijakan, merujuk laporan BRWA (2022) ada empat hal yang perlu direfleksikan ulang dalam percepatan pengakuan hutan adat: Pertama, pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) adat yang mahal dan butuh waktu lama. Kedua, minimnya komitmen dan tanggung jawab kepala daerah dan kepemimpinan untuk menyelenggarakan pengakuan masyarakat adat. Ketiga, rendahnya kapasitas kelembagaan dan staf untuk melaksanakan kegiatan teknis terkait penyusunan pedoman dan pelaksanaan tahapan-tahapan pengakuan masyarakat adat seperti yang diatur dalam kebijakan daerah, maupun peraturan perundangan lainnya. Keempat, rendahnya dukungan kepada masyarakat adat dalam proses pemetaan partisipatif wilayah adat dan fasilitasi penyiapan data yang memadai untuk pemenuhan persyaratan teknis dan substantif seperti yang diatur dalam kebijakan daerah maupun paraturan-perundangan.
Kebijakan politik percepatan pengakuan hutan adat juga penting disyarati dengan kualitas akurasi dan validitas data empirik yang kokoh. Terutama tentang dimensi sejarah tenurial, pemahaman yang utuh tentang sistem, kelembagaan, struktur sosial-budaya adat, politik lokal, serta kompleksitas dan berlapisnya hubungan masyarakat adat dengan tanah-air dan ruang hidupnya yang tak hanya bersifat ekonomistik, tetapi juga berdimensi politik, sosial-budaya, ekologis, bahkan religio magic/spiritual. Singkatnya, etnografi kritis (critical ethnography) adat mesti menjadi syarat wajibnya. Hal ini akan dapat membantu pemahaman dan pendalaman yang lebih uth menyeluruh atas masyarakat adat dan ruang hidupnya, serta lebih dapat menjauh terhindar dari jebakan glorifiksi dan sikap romantik atas komunitas masyarakat adat.
Jika pemenuhan hak dan kedaulatan masyarakat adat dirujukkan pada standar internasional melalui konsep humand security (keamanan insani) yang dirumuskan sebagai kebebasan dan keamanan dari semua ketakutan serta pencapaian kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan manusia, maka perlu dilakukan refeksi ulang apakah syarat-syaratnya telah terpenuhi atau menjadi dampak positif dengan kebijakan pengakuan hutan adat itu. syarat tersebut adalah keamanan atas pangan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, komunitas, pribadi dan politik.
Pemenuhan syarat keamanan insani, yang mulai banyak dipraktikkan di banyak negara di dunia ini, dianggap menjadi penentu dan tiang utama dari keamanan suatu negara. Maka, negara mesti didorong untuk berpartisipasi aktif dan penuh dalam pembentukan dan pemenuhan keamanan inividu, sebab negara dapat terkena dampak dari ketidakamanan warga negaranya, termasuk kemanana insani dari masyarakat adat yang masih hidup dan tergantung dari hutan dan ekosistem tradisional mereka.
Dengan demikian, untuk mewujudkan kedaulatan agraria masyarakat adat, tampaknya pengakuan legal serta membuka akses “hak kelola” atas hutan dan alam mereka semakin tidak cukup. Negara juga mesti memastikan pemenuhan hak dasar dan syarat “kedaulatan” penuh msyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya sebagaimana disyaratkan dalam konsep Keamanan Insani. Tanpa syarat kedaulatan atas tanah-air dan ruang hidup masyarakat adat belum sepenuhnya dapat keluar dari ancaman ekspansi kebijakan pembangunan nasional yang watak dasar perilaku dan ideologisnya hingga kini belum berubah secara mendasar, yakni kapitalistik, pertumbuhan minus pemerataan-keadilan, oligarkis, eksploitatif-ekstraktif dan komoditifikasi atas sumber-sumber agraria. Maka, selain pentingnya pengesahan Undang-undang Masyarakat Adat sebagai dasar hukum nasional, gagasan reforma agraria kehutanan dalam makna perombakan ketimpangan struktural agraria (kepemilikan, penguasaan, distribusi, akses dan pemanfaatan) sumber-sumber agraria nasional, khususnya di wilayah masyarakat adat makin relevan untuk diwujudkan.
*Tulisan ini telah dimuat di Koran Tempo, 17 Agustus 2022