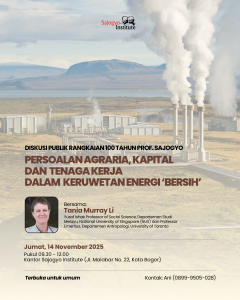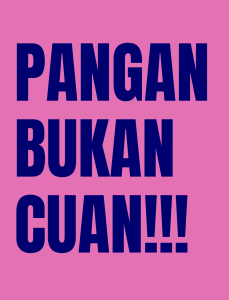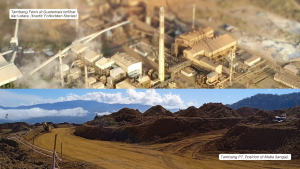Kiagus M. Iqbal
Gizi merupakan indikator vital dalam menilai berhasil tidaknya pemerataan pembangunan di Indonesia. Karenanya, pemenuhan gizi nasional adalah kewajiban pembangunan yang harus dipenuhi Negara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pemerintah resmi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Perpres No. 83/2024, 15 Agustus 2024 lalu. Badan Gizi Nasional memikul tugas berat pemenuhan gizi nasional: memenuhi target penurunan stunting dan wasting Balita masing-masing 14 persen dan 7 persen. Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab atas program bantuan pangan gratis dengan anggaran bejibun Rp 71 Triliun.
Hingga 2023, Indonesia masih jauh dari target penurunan tingkat stunting mencapai 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dibanding tahun 2022 (21,6 persen). Tak hanya itu, Pemerintah tidak berhasil mengerem naiknya tingkat wasting hingga level 8,4 persen (2023), naik 0,7 persen dibandingkan tahun lalu (7,7 persen). Jika seorang anak yang mengalami wasting tidak ditangani, maka sang anak berpotensi 3 kali lipat mengalami stunting (UNICEF, 2023). Berdirinya Badan Gizi Nasional membawa misi penting penurunan tingkat stunting dan wasting anak balita di Indonesia.
Namun, terdapat tiga catatan kritis terhadap pembentukan Badan Gizi Nasional agar misi pentingnya dalam pemenuhan gizi nasional sekaligus percepatan penurunan stunting dan wasting dapat terpenuhi. Sekaligus, anggaran pangan gratis bejibun dapat tepat sasaran dan tidak terbuang percuma
Paradigma Usang Kebijakan
Pembentukan Badan Gizi Nasional masih tidak lepas dari tiga permasalahan. Pertama, paradigma kebijakan pangan dan gizi nasional masih bertumpu pada ‘ketahanan pangan’. Paradigma tersebut berkutat pada penyediaan pangan yang bergantung pada mekanisme pasar pangan global yang rentan dan tidak pasti (McMichael, 2020).
Ketersediaan pangan yang bergantung pada persediaan stok pasar semata rentan terhadap volatilitas harga dan kelangkaan stok yang berada di luar kendali negara. Gawatnya, Perpres No. 81/2024 sebagai aturan penunjang jalannya Badan Gizi Nasional melalui pengaturan percepatan penganekaragaman pangan tidak lepas dari paradigma kebijakan pro-pasar sebagai tumpuan utama dalam penyediaan aneka ragam pangan. Dalam laporan Sensus Kesehatan Indonesia 2023, 39,1 persen anak di bawah 23 bulan di 21 provinsi mengalami ketidakragaman pangan. Kebijakan pangan nasional semacam ini menambah riskan memburuknya masalah gizi anak jika diserahkan pada mekanisme pasar yang tidak stabil dan rentan terhadap kontrol korporasi pangan besar yang menguasai sektor hulu hingga hilir.
Pemerintah pun masih belum selesai menyelesaikan problem kemampuan penyediaan pangan dalam negeri upaya memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Hal ini terlihat dengan menyusutnya kinerja subsector pertanian pangan hingga minus 3,88 persen pada 2023 (BPS, 2024). Penyusutan tersebut menyebabkan tingkat produksi pangan (khususnya beras) semakin menurun. Akibatnya, Indonesia mengalami tingkat kerentanan pangan yang mengkhatirkan jika melihat tingkat prevalensi kerentanan penduduk terhadap ketidakcukupan pangan dalam 4 tahun terakhir (BPS, 2023)
Kedua, paradigma struktur Badan Gizi Nasional amat elitis dan minim partisipasi. Jika diperhatikan seksama, Perpres ini tidak ditemukan kata kunci ‘Partisipasi’. Struktur Dewan Pengarah (Pasal 8) hanya diisi oleh pejabat-pejabat elit yang tidak bersinggungan langsung terhadap masalah gizi. Bahkan, tentara terlibat di dalam Badan tersebut. Ironisnya, Badan minim melibatkan partisipasi pihak-pihak yang jelas terkait langsung dengan masalah pangan dan gizi di lapang, seperti organisasi tani nasional dan local, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak langsung dalam masalah pangan dan gizi, Masyarakat Adat dan komunitas ahli gizi.
Ketiga, paradigma pemenuhan gizi nasional amat lekat dengan mental ‘memberi’ ketimbang mental ‘memberdayakan’. Hal ini tercermin dari Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 83/2024 di mana aturan hanya menjelaskan pihak-pihak yang menjadi sasaran pemenuhan Gizi Nasional. Perpres tersebut tidak memberikan ketentuan jelas dalam mematok siapa yang diprioritaskan dalam pemenuhan gizi nasional dan bagaimana mekanisme partisipasi para pihak-pihak sasaran tersebut agar mereka pelan-pelan berdaya lepas dari masalah gizi secara berdikari. Selain itu, sasaran pemenuhan gizi tidak memiliki keberpihakan yang jelas pada lapis masyarakat mana program tersebut yang akan disasar.
Pemenuhan Gizi yang Memberdayakan
Prof. Sajogyo (1983, 1986) telah jauh hari mengingatkan, pemenuhan gizi merupakan indikator penting berhasil tidaknya pemerataan pembangunan nasional. Mengingat peran Badan Gizi Nasional yang begitu penting dan urgen, ada tiga masukan penting agar Badan Gizi Nasional berjalan sesuai arah dan sasarannya.
Pertama, tumpuan kebijakan gizi harus berdasarkan paradigma kedaulatan pangan, yaitu pemenuhan ketersediaan pangan secara berdikari dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar pangan global. Badan Gizi Nasional harus memperkencang koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pangan Nasional dalam perbaikan di sisi produksi, khususnya menggalakkan reforma agraria yang benar merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah, perlindungan terhadap tanah-tanah pertanian produktif, mitigasi menghadapi kerusakan iklim dengan sasaran utama Petani Gurem dan Buruh Tani dan menjamin partisipasi organisasi tani lokal dan nasional dalam mengawasi penetapan harga gabah-beras dan subsidi input dan alat pertanian. Tak hanya itu, Pemerintah perlu untuk mengintegrasikan antara praktik pekarangan dan hutan rakyat serta memanfaatkan praktik pertanian tradisional di tingkat local dalam pemenuhan pangan dan gizi berbasis pangan local.
Kedua, Perpres No. 83/2024 harus meletakkan prinsip partisipasi aktif masyarakat di dalam Badan Gizi Nasional. Keterlibatan Komunitas Ahli Gizi, Organisasi Tani Nasional dan Lokal, Organisasi Perempuan, Masyarakat Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada masalah pangan dan gizi, dan Organisasi Non Pemerintah yang fokus terhadap masalah Pangan dan Gizi harus dilibatkan dalam Badan Gizi Nasional sebagai bentuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan checks and balances.
Ketiga, kebijakan pemenuhan pangan harus memiliki sasaran prioritas dan meletakkan prinsip dasar ‘pemberdayaan’. Berefleksi terhadap hasil riset Sajogyo dan kawan-kawan dalam Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (1973), sasaran utama program adalah para ibu menyusui dan ibu hamil. Para ibu menyusui dan ibu hamil dipilih sebagai sasaran utama karena kaum ibu merupakan kunci keberhasilan dan tanggung jawab pemenuhan gizi di tingkat keluarga. Para ibu tersebut bergabung dan terlibat aktif dalam wadah lembaga kerjasama swadaya desa dan pemerintah pusat melalui Taman Gizi.
Lembaga Taman Gizi di Desa sasaran meletakkan paradigma perbaikan gizi yang memberdayakan. Artinya, Taman Gizi tidak sekadar memandang sasaran prioritas sebagai objek penerima bantuan perbaikan gizi an sich, namu menjadi subjek aktif yang terlibat dan ikut mengorganisir lembaga Taman Gizi. Program UPGK dibuat bukan sebagai lembaga pemberi bantuan dalam jangka panjang. Program mematok jangka waktu tiga-empat tahun pemberdayaan sebelum Taman Gizi di desa sasaran menjadi lembaga mandiri di desa.
Atas dasar refleksi tersebut, Badan Gizi Nasional perlu memperjelas sasaran prioritas dalam program pemenuhan gizi. Jika jumlah anak balita Indonesia sebanyak 18.104.900 jiwa (Susenas BPS 2023) dan rata-rata satu ibu memiliki dua anak, maka perlu menyasar 1.946.277 ibu pengasuh, 21,5 persen (3.892.554 jiwa) anak balita stunting, 769.458 ibu pengasuh dari 8,5 persen (1.538.917 jiwa) anak balita wasting. Rata-rata pekerjaan kepala keluarga dari anak penderita stunting dan wasting adalah nelayan, petani dan buruh tani, buruh, sopir dan pekerja rumah tangga, ditambah mereka yang tidak bekerja (baik pengangguran terbuka atau pengangguran terselubung). Para ibu dari lapis inilah yang seharusnya menjadi sasaran prioritas dalam program pemenuhan gizi dan diharapkan dapat diajak berpartisipasi aktif di dalam program pemenuhan gizi agar mereka dapat berdaya melepas masalah gizi sang anak dalam jangka waktu tertentu.
Selain itu, perlu kerjasama riset bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di akar rumput dalam riset penajaman sasaran prioritas pemenuhan gizi. Riset ini penting khususnya dalam mempertajam siapa saja subjek sasaran prioritas di masing-masing provinsi yang mengalami tingkat stunting dan wasting di atas rata-rata nasional. Riset ini penting dilakukan agar penggunaan anggaran pangan yang besar dapat terukur, tepat sasaran, jelas dalam eksekusi program, bahkan berpotensi menghemat anggaran.
Dengan meletakkan paradigma kebijakan pemenuhan gizi yang berdaulat pangan, memberdayakan dan berpihak pada lapisan masyarakat paling lemah, Badan Gizi Nasional diharapkan mampu menjadi lembaga pemenuhan dan perbaikan gizi sekaligus membawa Secercah harapan pemerataan pembangunan menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.