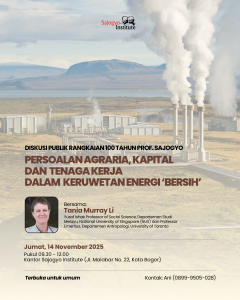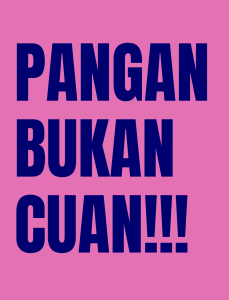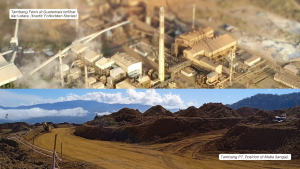Kiagus M. Iqbal
Baru-baru ini, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini dibuat dengan tujuan perbaikan tata kelola usaha di dalam kawasan hutan (pertambangan, perkebunan dan kegiatan lainnya) demi optimalisasi pendapatan negara (Pasal 2 ayat 1). Meski begitu, aturan ini problematik dengan posisi aktor-aktor secara asimetris antara korporasi dan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Ini terlihat dari pengenaan hukuman pidana terhadap Orang yang memiliki perizinan berusaha dan tidak (Pasal 4).
Terlebih, tugas pengawasan dan pelaksanaan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan semakin dalam melibatkan militer. Ada kecenderungan aturan Perpres ini semakin memperdalam keterlibatan tentara demi melindungi usaha-usaha besar yang bergerak di dalam Kawasan Hutan. Hal ini akan melahirkan tuduhan terhadap militer penuh dengan konflik kepentingan dan kepentingan-kepentingan terselubung dalam bisnis militer di dalam kawasan hutan.

Pelibatan militer terhadap penguasaan hutan sebenarnya memiliki akar yang dalam secara historis di Indonesia. Terdapat persepsi yang kontradiktif dalam memaknai hutan di Jawa. Pada satu sisi, hutan dipercaya sebagai wilayah gelap dan liar, tempat para roh-roh jahat bersemayam sejak zaman Majapahit. Seringkali, orang-orang yang hidup di hutan dicap sebagai orang pinggiran peradaban dengan cara hidup yang terbelakang (budaya ladang gilir balik, berburu-meramu dan hidup nomaden, sehingga susah diatur dan dikuasai). Karenanya, hutan harus ditaklukkan dengan ‘gerakan’ pemberadaban seperti memperkenalkan tinggal hidup menetap, membentuk sistem pemukiman memusat, dan sistem pertanian sawah menetap intensif.
Di sisi lain, hutan menjadi tempat para kesatria bangsawan melepas segala atribut keduniawian menuju kehidupan yang lebih sempurna dan menuju nirwana. Mereka menyingkir dari kehidupan duniawi dan bertapa menuju keheningan dan ketenangan hingga waktunya ia melebur bersama alam-hutan. Itulah konsep moksa yang terkenal. Karenanya, hutan dimaknai sebagai pintu menuju kehidupan selanjutnya, menuju swarga yang nirwana.
Hutan kerap diasumsikan penguasa sebagai wilayah politis dan sumber instabilitas status kekuasaan bertahan yang senantiasa harus diawasi. Karenanya, tindakan membuka hutan (babad alas) di masa lalu sebagai bentuk tindakan politis yang memiliki dua wajah: menyingkir dari beban berlebih akibat kekuasaan yang sewenang-wenang, tindakan yang biasanya dilakukan para petani; atau mengasingkan diri dan tempat mengkonsolidasikan pemberontakan menghadapi kekuasaan raja lalim.
Perpindahan petani ini pernah terjadi pada masa-masa Mataram Hindu pada abad 8-9 di masa pembangunan Borobudur dan Prambanan. Perdebatan antara Soe Hok-gie dan Ong Hok Ham mengenai pembangunan Borobudur dan Prambanan menjadi anekdot penting mengenai konsekuensi pembangunan ambisius kedua candi fenomenal itu: terjadi perpindahan besar-besaran penduduk di sekitar wilayah candi akibat beban kerja yang terlalu berat. Perpindahan penduduk juga pernah terjadi di Karesidenan Madiun akibat praktek Tanam Paksa pada 1830-1870: tindakan rasional demi menyelamatkan keluarga petani yang terlanggar ambang subsistensinya.
Tindak buka hutan kerap distempel tindak pemberontakan terhadap kekuasaan bertahan. Dasar pikir hutan sebagai wilayah liar dan biadab lahir akibat hutan dianggap tempat pelarian para kriminal-kriminal pengacau dan kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap tindakan Raja. Cerita Arok sebagai cikal bakal pendiri Singosari, rahim kerajaan-kerajaan Jawa selanjutnya, mulanya ber-candradimuka di dalam hutan bersama para Brahmana mengkristalisasikan mental perlawanan dan penggulingan kekuasaan Tunggul Ametung dalam Roman Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer. Babad Alas Jaka Tingkir di pedalaman Jawa demi lahirnya Kerajaan Pajang merupakan bentuk pemberontakan terhadap Kerajaan Demak di pesisir; pemberontakan Trunojoyo terhadap Amangkurat I dan II tidak lepas dari pertahanannya di pedalaman hutan, hingga geger pecinan yang dipimpin Sunan Kuning yang menghancurkan Kartasura tidak lepas dari kawasan hutan sebagai basis perlawanannya.
***
Pola penguasaan wilayah (teritorial) sebenarnya terkesan longgar dalam kerajaan-kerajaan Jawa. Sistem politik penguasaan di Jawa didasarkan pada pengaruh wahyu dan kesakten Raja. Ibarat lentera di dalam wilayah lingkaran, semakin jauh dari pusat lingkaran semakin temaram pengaruh dan kekuasaan sang raja. Karenanya, dikenal pembagian wilayah berdasarkan pengaruh: negara (ibukota, tempat kedudukan Raja, negaragung, wilayah inti di sekitar negara, dan mancanegara yaitu wilayah-wilayah kerajaan terluar.
Sistem kekuasaan Raja pra-kolonial hanya mengontrol dua hal, pertama kontrol terhadap penduduk sebagai sumber kekuatan politik (patron-klien, manunggaling kawula gusti) dan pemasukan ekonomi Raja dan keluarganya berupa pajak, upeti dan kerja bakti. Artinya, kekuasaan dipusatkan demi menjaga bertahannya tenaga kerja yang dapat dieksploitasi surplus hasil tenaga kerjanya. Sedangkan kekuasaan teritorial wilayah dianggap tidak diperlukan mengingat perimbangan penduduk dan luasan tanah masih begitu besar tidak memerlukan kontrol teritori wilayah.
Masuknya Kompeni VOC ke Jawa mengincar hutan Jati di pesisir utara melahirkan benih-benih kebijakan teritorialisasi dengan masuknya pengelolaan kehutanan ilmiah yang mengontrol dua hal: spesies (Jati) dan tenaga kerja (eksklusi masyarakat dari desa menjadi buruh tebang dan angkut kayu). Pengelolaan tersebut bersifat eurosentris di mana keberpihakan pengelolaan tertuju pada eksploitasi berlebih demi akumulasi kapital, sedangkan saat hutan jati telah semakin sempit dan sedikit, kebijakan konservasi menjadi tameng demi meneguhkan penguasaan atas hutan jati, lalu kawasan hutan secara umum pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kebijakan hutan ilmiah mengasumsikan hutan semakin sempit dan setiap tindakan membuka hutan adalah ancaman terhadap konservasi sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan hutan yang keras. Pendekatan kekerasan dengan penjagaan polisi hutan dan bantuan militer menjadi keniscayaan.
Mereka yang selama ini hidup dari hutan seperti Masyarakat Kalang mengalami penindasan akibat perlawanan mereka terhadap pembatasan ekstrem akses ke hutan. Perlawanan mereka berkisar pada pembatasan akses hutan akibat pengenaan pajak terhadap mereka dalam mengakses hutan, hasil hutan, dan perdagangan hasil hutan. Beban yang berat sekaligus menginjak identitas mereka , Masyarakat Kalang, sebagai pihak yang hidup dari hutan dan memiliki sejarah pengakuan panjang dalam akses dan pengelolaan usaha hutan jati, ditumpas secara militer, dihapus dalam arena sejarah, dan dicap sebagai orang pinggiran, liar, dan pemberontak keras kepala.

Eksklusi dari hutan semakin diperteguh dengan aturan Undang-Undang Kehutanan 1865 dan Aturan Agraria 1870 dengan asas domeinverklaring-nya. Aturan-aturan tersebut sebenarnya semakin memperteguh status quo kekuasaan di Jawa dengan konsekuensi pembatasan perpindahan penduduk melalui babad alas. Pembatasan itu memperteguh raja-raja Jawa dalam kontrol terhadap mobilitas penduduk, tindakan politis yang mengancam, dan memastikan pundi-pundi ekonomi terhadap kerajaan yang bekerjasama dengan Belanda berjalan mulus. Jika di masa lalu, kerajaan-kerajaan Jawa selalu mengalami instabilitas akibat pemberontakan-pemberontakan yang berbasis di hutan (mendorong setiap bangsawan adalah bertindak sebagai prajurit militer yang setiap saat dapat bergerak untuk menumpas dan berperang), dengan adanya tindakan kolonial terhadap pembatasan akses hutan memperteguh kontrol stabilitas politik Pemerintahan.

Jika ditarik ke masa setelah kemerdekaan, hutan pada akhirnya tetap memiliki identitas politis yang mengganggu pemerintahan bertahan, seiring pergantian rezim: Belanda yang kewalahan karena strategi perang gerilya yang berbasis di desa dan hutan, perlawanan-perlawanan DI/TII dan PRRI/Permesta yang berbasis perlawanan di pedalaman hutan Jawa Barat dan Sulawesi-Sumatera, dan berbagai pemberontakan-pemberontakan akhir ini di Poso dan Papua bertahan basis di hutan-hutan.
Karenanya, tindakan-tindakan penertiban kawasan hutan merupakan hasil daftar panjang militerisasi kawasan hutan sejak datangnya Belanda menguasai hutan-hutan Jawa dengan pendekatan kehutanan ilmiah. Selama kebijakan hutan ilmiah dipraktekkan, pendekatan militer akan selalu hadir di sana. Dan agaknya, Pemerintah hari ini masih melestarikan kebijakan kehutanan semacam itu. Apakah kita tidak beranjak dari pola pikir kolonial?
Bacaan lanjutan:
- Cornelis Van Vollenhoven (2020), Orang Indonesia dan Tanahnya, Yogyakarta: INSIST Press
- Nancy Lee Peluso (2006), Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan, Yogyakarta: KOPHALINDO
- Onghokham (2018), Wahyu Yang Hilang, Negeri Yang Guncang, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Onghokham (2018), Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad IX, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Soemarsaid Moertono (1981), Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia