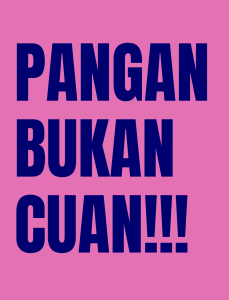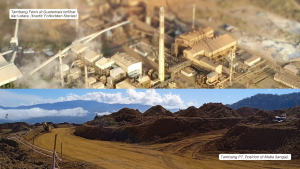Eko Cahyono
Peneliti/Pegiat Sajogyo Institute. Sekretaris Yayasan Sajogyo Inti Utama. Direktur Eksekutif Sajogyo Institute 2015-2018. Asisten Pengajar di Fakultas Ekologi Manusia, IPB.
Seolah kedap suara nurani rakyat, akhirnya RUU Omnibuslaw atau Cipta Kerja usulan Pemerintah itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 5 Oktober 2020 lalu. Meski dengan versi yang beragam dan catatan masih ‘dirapikan’ akibat ‘salah ketik’.
Penolakan dan protes keras berbagai elemen masyarakat, baik kaum buruh, akademisi, agamawan, gerakan mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya, terhadap proses pengesahan RUU Cipta Kerja, tak dihiraukan, proses dipercepat dikebut siang malam, menerabas larangan sidang di hari libur dan inkonsistensi perintah nasional “di rumah saja” akibat wabah pandemik Covid 19. Sebenarnya, siapa yang hendak dilayani?
Hasil “Sudah Membaca!” Yang Diabaikan
Para pengambil kebijakan baik Eksekutif maupun Legislatif dan para tim ahlinya sebenarnya telah lama diberikan beragam dokumen dan informasi publik tentang argumen, kritik dan alasan penolakan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja. Terutama seputar penyediaan karpet merah gelombang tsunami investasi yang nir-keadilan sosial-ekologis dengan mega proyek dalam koridor ekonomi (Sajogyo Institute, 2020), ancaman kembalinya sentralistik kekuasaan pusat ala Orde Baru dan pelucutan kewenangan daerah (KPPOD, 2020), potensi pengingkaran hak dasar buruh, pekerja, petani dan pemunduran upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM, 2020), ancaman pelanggengan komoditifikasi, eksploitasi dan perusakan sumberdaya alam (ICEL, Walhi, Jatam, 2020), pengingkaran mandat Reforma Agraria, perluasan konflik agraria struktural dan perampasan ruang hidup petani dan masyarakat adat (KPA, AMAN, 2020), dan menyalahi prosedur pembentukan Undang-undang, pengabaian partisipasi dan potensial mencipta hyper-regulated baru (Tim FH UGM, PSHK, YLBHI, 2020), ancaman liberalisasi multi sektor (pertanian, pendidikan, kehutanan, pertambangan) yang akan memperburuk kualitas dan jaminan keberlanjutan lingkungan dan hak hidup (Koalisi 200 Guru Besar/Akademisi Tolak Omnibuslaw).
Organiasi NU, Muhammadiyah, dan koalisi Pemuka Lintas Agama juga menegaskan penolakannya dengan dasar kebijakan menarik ivestasi tidak serius mendengar aspiarsi rakyat, absennya perlindungan lingkungan, hak atas pangan dan sosial-ekonomi rakyat, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas konsttuisi. Dan tentu saja masih banyak lagi laporan otoritatif baik dari individu maupun kelompok yang telah “membaca serius” dokumen RUU Ciptaker dalam bergam versinya itu. Sehingga, sulit diterima akal sehat, bila bantahan yang kerap muncul dari Pemerintah dan DPR adalah karena “tidak membaca” dan “tidak faham” susbtansi RUU Ciptakerja.
Publik juga patut mengingat bahwa komposisi fraksi-fraksi yang setuju pengesahan RUU Ciptaker adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, dan hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker. Menarik memahami bagaimana argumen penolakan Partai Politik yang berada di dalam sidang tersebut. Partai Demokrat misanya, dalam pandangan mini fraksi, menyebut beberapa alasan work out dan penolakan mereka, yakni: Pertama, Ada pengesahan mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak ideal dilakukan, terlalu cepat dan terburu-buru. Akibatnya, pembahasan pasal per-pasal tidak mendalam; Kedua, RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila. Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik; Ketiga, RUU Cipta Kerja memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural. Dalam pembahasannya, RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil society secara serius. Tanpa pembahasan yang komprehensif maka sebagai produk hukum RUU Cipta Kerja akan berat sebelah dan tidak memenuhi asas berkeadilan sosial.
Sebagai satu pernyataan politik, menarik untuk terus diuji ulang konsistensi sikapnya ke depan. Namun, yang patut pertanyakan lebih mendasar adalah seluruh kemudahan dan “climate investasi” melalui UU Ciptaker itu sebenarnya menjawab masalahnya siapa? Sebab seringkali, kemudahan investasi diklaim dan kaitkan dengan tujuan pembangunan dan perbaikan kondisi ekonomi nasional yang diasumsikan secara liner dengan kesejahteraan rakyat. Mari melampaui debat kusir soal bad or good investasi. Yang pasti, tak tak ada yang tak ingin pembangunan dan perubahan lebih baik di negeri ini. Tapi, apa sebenarnya akar masalah rakyat hari ini, kok karpet merah investasi Omnibuslaw UU Cipta Kerja, jawabnya? Apakah syarat-syarat kedaulatan dan keadilan sosial-ekologis telah terpenuhi sebagai dasarnya? Siapa yang sebenarnya paling banyak diuntungkan dan dirugikan model kebijakan pembangunan “ramah investasi”? Dan, apakah investasi berarti mengurangi ketimpangan struktural atau sebaliknya, malah melanggengkan? Dari peta ketimpangan yang terjadi, tentu saja investasi hanya berputar di kelompok elit oligarki
Kuasa Oligarki Pengabdi Investasi
Laporan Bank Dunia (2018) yang menyebutkan 4 ketimpangan, salahsatunya adalah persoalan pemusatan kekayaan yang tinggi di Indonesia. Sebanyak 10 persen orang kaya memiliki 77 persen seluruh kekayaan negara. Pundi-pundi uang yang didapat dari aset finansial dan fisik mengalir hanya ke kantong para orang kaya sehingga penghasilan yang didapat lebih besar. Korupsi menjadi salah satu alasan di balik munculnya fenomena pemusatan harta kekayaan ini. Laporan Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TP2K, Oktober 2019) lalu menunjukkan bahwa 1% orang di Indonesia bisa menguasai 50 persen aset nasional. Jika dinaikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Catatan akhir tahun 2019 dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) juga mesnegaskan salahsatu akar masalah kebangsaan ekarang adalah ketimpangan, ‘intolerasi ekonomi’ akibat oligarki.
Bercokolnya oligarki membuat kue ekonomi nasional tumbuh, tetapi tidak merata. Koefisien gini turun sedikit, begitu pun rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia atau 150 juta orang. Dalam hal ketimpangan struktural juga bisa dicerminkan masih tingginya penguasaan lahan oleh segelintir orang dan kelompok koorporasi tertentu. Dalam kasus sektor kehutanan, kooporasi sawit dan tambang masih menjadi penguasa lahan skala luas. (TuK, FWI, Auriga, 2018). Ketimpangan juga bisa dilihat dari aspek ketidakadilan distribusi dan alokasi atas tanah dan sumber agraria nasional yang masih tinggi, jauh dari tujuan pemerataan dan keadilan agraria (Shohib, 2019). Tak heran jika daftar rangking orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes (2018-2019) juga tidak banyak berubah. Jika demikian masalahnya, para elit dan penguasa politik yang siang-malam memaksa lahir aborsi Omnibuslaw itu sebenarnya mengabdi kepada siapa? Kepentingan Rakyat atau kuasa gurita pemilik modal dan investasi?
Yang jelas, melalui akrobat politik dalam sidang pengesahan RUU Cipta Kerja kontraversial itu, kini rakyat semakin faham watak asli sebagian besar penguasa di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, yang tidak pernah sungguh-sungguh mewakili representasi suara basis konstituennya sendiri. Yang justru terbukti adalah, semakin telanjang dan kuatnya layanan dan pengabdian mereka pada para cukong dan korporasi rakus investasi sponsornya sendiri. Hal ini mengkonfirmasi temuan KPK (2017) yang menyebutkan 70 % lebih para penguasa politik tersandera “ijon politik” dengan korporasi (sumberdaya alam), baik di PILKADA maupun PILPRES, dengan kompensasi kemudahan ijin dan konsesi proyek investasi mereka.
Terlebih, jika mengingat status 263 atau sekitar 45, 5 % dari 575 anggota DPR diduga terafiliasi dengan perusahaan. Nama mereka tercatat pada 1.016 perseroan terbatas yang bergerak di berbagai sektor (Yayasan Auriga, 2020). Inilah sebenarnya potret gamblang yang disebut sebagai jenis oligarki ‘Penguasa Kolektif’ yang terhubung dengan watak ‘Oligarki Sipil’, yang memiliki ciri-ciri umum kuatnya kaitkelindan relasi kuasa dan bersatunya semua kepentingan negara (eksekutif), legislatif, yudikatif, akibat dari komposisi mayoritas elit penguasanya: Politisi cum penguasaha/pebisnis (JA. Winter, Oligarki, 2011).
Mayoritas para aktor utamanya adalah hasil proses ‘reorganizing’ dan transformasi kekuatan politik oligarki warisan Orba yang masih bercokol kuat hingga sekarang. Bedanya, jika di era Orba kekuatan oligarki “predatoris” ini melanggengkan dominasinya melalui instrumen otoritas sentral negara, di era Pasca Suharto, dilakukan melalui berbagai partai politik, pemilu, parlemen dan disentralisasi (Vedi R Hadiz, 2005). Studi terbaru tentang Peta Pebisnis di Perlemen (Marepus Corner, 2020) menyebut 55 % Pebisnis multi sektor usaha, menguasai di DPR sehingga melahirkan syarat kepentingan atas produk legislasinya, dan makin mengukuhkan jejaring oligarki nasional.
Akhirnya, terbitnya UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw mesti dimaknai sebagai tonggak penting ‘kemenangan’ oligarki para pengabdi investasi, sekaligus lonceng tanda kematian suara nurani dan masa suram demokrasi di negeri ini. Jika tujuan mulia konstitusi saja bisa diingkari, teramat mudah titipan amanat suara rakyat dikhianati. Beragam aksi telah dimulai, saatnya, obor reformasi dinyalakan kembali.
Tulisan ini telah dimuat di situs media online Bintang Muda Indonesia pada 19 Oktober 2020. Sumber tautan tulisan di sini.