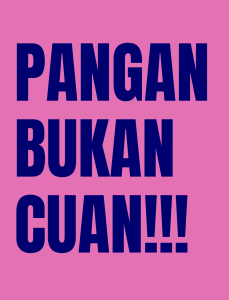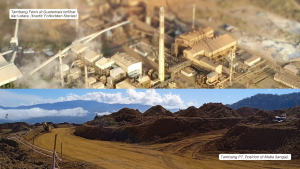Penulis: Eko Cahyono**
Tahun 2020 masa berat. Kalau menghitung dari awal pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), akhir 2019, kini makin kuat rasa kehilangan dan duka cita, dari keluarga, kerabat dekat maupun kenalan. Penanda paling mudah dengan makin meluas dampak dan korban pandemi di negeri ini, juga dunia. Tak hanya di kota besar, di kampung dan desa juga demikian.
Data Satgas COVID-19 per 31 Desember 2020 menyebutkan, 743. 198 orang terkonfirmasi positif, naik 8.074 orang, meninggal dunia 22. 138 orang, tambah 194 orang dari hari sebelumnya.
Anehnya, meski kengerian dan horor itu di depan mata, tak semua masyarakat percaya penuh. Dampaknya, kesadaran publik masih rendah untuk waspada, meski ancaman “gelombang kedua” pandemi ini diwartakan serius beragam media. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut hemat penulis setidaknya ada empat akar masalahnya.
Empat akar masalah
Pertama, rendahnya konsistensi aturan formal. Dinamika naik turun perubahan aturan dan status kondisi nasional dan di daerah tentang COVUD-19 membuat masyarakat luas merasa situasi pandemi bukan bahaya serius. Ketegasan aturan sempat dilakukan, namun seringkali hangat di awal adem kemudian. Padahal, dalam situasi sekarang, perlu ketegasan dan pendisipilnan, bahkan sanksi tak pandang bulu. Dinamis dan masih longgar aturan ruang publik, di mall dan moda transportasi (darat dan udara) menjadi contoh aktualnya.
Kedua, luruhnya keteladanan. Ajakan dan kampanye pencegahan atas pandemi seringkali bertolak belakang dengan realitas keseharian yang diasaksikan publik. Masih dijumpai, tokoh nasional dan daerah atau pejabat negara lain seringkali justru merayakan hajatan mereka dengan “memaksakan” diri tetap seperti kondisi baik-baik saja.
Kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi, meski diklaim bebas dari klaster penularan, secara moral sangat memukul kesadaran publik luas. Ia seperti ada “standar ganda.” Satu sisi tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan dilarang buka, untuk pilkada aturan-aturan itu berubah prosedural semata.
Kemudian “new normal” sebenarnya, untuk siapa?
Ketiga, minimnya peluang alternatif harapan. Banyak dijumpai kenekatan masyarakat tetap aktif bekerja dengan dasar utama lebih menjaga tetap bertahan hidup. Tak lebih.
Bagi kalangan menengah ke atas bisa jadi, peluang dan alternatif bertahan hidup bisa lebih banyak pilihan. Bagi rakyat di lapis sosial terbawah, dengan ekonomi harian/mingguan, kalau tak bergerak artinya ancaman keberlanjutan hidup.
Sumbangan dan bantuan sosial pasti membantu dalam jangka tertentu, namun bukan jaminan penentu dalam jangka panjang kehidupan. Watak dasar program charitiy adalah belas kasihan. Sedangkan yang rakyat perlukan adalah bangkitnya kemandirian bahkan kedaulatan.
Pahitnya, rakyat malah menyaksikan, seorang menteri sosial masih tega mengkorupsi bantuan sosial.
Keempat, ganguan multi tafsir. Gejala nomophobia (no mobile phone phobia) yang makin kuat di era pendemi, mencipta ketergantungan masyarakat pada sumber berita di media online. Kuatnya silang pendapat lalu lintas multitafsir atas wabah COVID-19, baik berbasis teori konspirasi global, tasfir teologis, tafsir medis, bahkan politis sedikit banyak memiliki pengaruh tingkat kepercayaan atas dampak pandemi COVID-19, di masyarakat luas yang sejatinya tak merata dasar pengetahuan dan simetri informasinya.
“Tenaga dalam” rakyat
Empat hal di atas mesti jadi refleksi serius. Sebenarnya, kebijakan politik negara selama ini telah menyelesaikan akar masalah yang mana? Kalau masih level “prosedural” semata, sebagaimana praktik politik sistem demokrasi nasional sekarang, lalu hakektanya negara mengabdi kepada siapa? Tentu saja, tak pernah ada menu dan resep tunggal. Setidaknya, dasar-dasar konstitusioal bangsa telah memberi pondasi arah kiblat politik kepemihakan pendirian Republik Proklamasi ini.
Belajar dari Bung Hatta, dalam Mendayung Antara Dua Karang (1948), pasca merdeka semestinya bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, bukan tersangkut di salah satu karang seperti sekarang ini: kapitalisme dan neoliberalisme. Padahal, sistem neo-liberalisme tak pernah menghasilkan kesempatan kerja dan kesejahteraan untuk semua, malah mengakibatkan kesenjangan sosial yang makin besar.
Kekayaan pindah dari lapisan bawah ke lapisan atas. Hakekat proyek neoliberal meremukkan watak sosial hidup bersama. Watak dasar inilah juga yang menjiwai panduan resep solusi ekonomi dan politik nasional yang masih berat mengabdi ke pasar dan korporasi besar.
Komuditifikasi sumber-sumber agraria nasional masih jadi idola, menjauh dari cita-cita kemandirian dan kedaulatan. Hingga menjadi penting agenda merawat kemungkinan hidup bersama dari kolonisasi proyek neoliberal di era abad 21 ini. (HB. Priyono, 2006).
Tak heran, masih minim kebijakan pengakuan dan penyedian ruang khusus afirmatif untuk ragam inisitaif dan kekuatan dari “tenaga dalam” rakyat sendiri, meski telah terbukti resiliensinya hadapi ragam dampak pandemi.
Titik-titik pijar ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi lokal, ekonomi nusantara, atau dengan sebutan lain, dengan syarat kemelekatan nilai kekayaan pengetahuan dan kearifan yang menjiwainya layaknya tergali dan dikembangkan sebagai alternatif.
Merujuk hasil studi awal Wahana Lingkungan Hidup (Walhi, 2019) terdapat delapan rambu-rambu prinsip untuk pemulihan ‘ekonomi nusantara,’ yakni, pertama, keadilan sosial-ekologis, kedua, penghormatan tinggi pada khazanah pengetahuan dan kearifan sendiri, ketiga, menghormati keselarasan dan keberlanjutan ekosistem. Keempat, mengedepankan jaminan keselamatan rakyat di atas orientasi keuntungan ekonomi, kelima, menolak komoditifikasi sumberdaya alam semata demi tujuan dan kepentingan pasar.
Keenam, menegasan kompleksitas hubungan manusia dengan alam dan ruang hidup, bukan sekadar hubungan ekonomistik, ketujuh, keberlanjutan produktivitas rakyat dengan penegasan masyarakat sebagai subjek perubahan mereka sendiri, kedelapan, bertujuan mendorong inisiatif pembalikan dan pemulihan krisis sosial ekologis.
Singkatnya, berdasarkan 10 lokasi riset yang tersebar di enam lanskap ekologis ini menunjukkan, ada tak ada negara, mereka bisa hidup mandiri dan berdaulat secara sosial-ekonomi dan budaya.
Riset ini dilakukan di delapan provinsi, yaitu, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Bali, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Titik balik peradaban
Selain refleksi kritis sistem ekonomi-politik nasional, seyogyanya pandemi yang belum berujung ini membawa refleksi kepada pondasi peradaban lebih luas, baik bagi bangsa, pun dunia.
Belajar dari Titik Balik Peradaban (F. Capra, 1997) yang menegaskan, munculnya jenis virus baru, kriminalitas, dehumanisasi, krisis sosial-ekologis, perlombaan nuklir, bencana alam, inflasi, krisis energi, dan lain-lain, adalah residu peradaban yang tak terjawab janji modernisme. Makin terbukti ‘kegagalan’ paradigma mekanistik (mechanical thinking) Newtonian-Cartesian yang memisahkan antara ruh dan materi, sains dan spiritualitas dari suatu ilmu pengetahuan, hingga kehidupan di bumi ini dianggap laksana seonggok mesin.
Inilah salah satu yang dianggap penyebab kemunduran peradaban. Untuk itu, perlu cara pandang baru yang disebut systems thinking atau holistic thinking, yang memandang segala sesuatu secara keseluruhan, saling terkait dan tak terpisahkan satu sama lain.
Logonstrisme budaya “timur” termasuk nusantara sebenarnya memiliki akar dan tradisi holistik sejenis ini. Tak heran kalau pernah satu masa dalam babakan sejarah nusantara, negara-negara selatan pernah menguasai negara-negara utara. Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit (1478 M) membuat nusantara yang pernah jadi mercusuar dari selatan (Asia)–yang selalu mendominasi utara–, harus menerima kenyataaan bahwa arus yang selama ini berjalan, telah berbalik. Pada akhirnya, nusantara harus menerima kenyataan sekian abad lamanya terjajah (oleh negara-negara utara), (Toer, 1995).
Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu refleksi menarik adalah ajakan melihat ulang: “Matahari itu Berkah Atau Kutukan?” (Agusyanto, 2013). Pertanyaannya: pertama, mengapa daerah yang benar-benar subur (yang disebut sebagai surga) umumnya negara-negara tropis disimpulkan sebagai awal dan pusat peradaban manusia?
Kedua, mengapa masyarakat dengan teritori geografis berkelimpahan (subur dan kaya sumberdaya energi/pangan) di negara tropis, kehidupan justru tidak sejahtera? Sebaliknya, masyarakat dengan teritori “miskin” (negara-negara non –tropis) justru hidup lebih sejahtera?
Ketiga, mengapa kenyataan masyarakat di daerah tropis yang berlimpah sumberdaya energi/pangan justru lebih banyak didominasi masyarakat daerah non-tropis yang kerap mengalami “krisis pangan”? Apakah lantaran mereka tak mampu memanfaatkan berkah sinar matahari yang selalu bersinar sepanjang tahun di teritorinya?
Keempat, mengapa masyarakat non-tropis justru berhasil memonopoli kekayaan alam masyarakat tropis itu, dan mereka melakukan tanpa memikirkan nasib pemilik kekayaan alam yang dikuasainya? Inilah yang disebut sebagai jerat budaya sontoloyo.
Padahal, sejarah nusantara dengan kekayaan komoditas tropis, sejak barus, gaharu, cengkih, kayu manis, pala dan rempah-rempah lain, kopi, gula, cokelat, karet alam, tembakau dan seterusnya sudah diakui sebagai primadona ekonomi dunia. Ia juga mempengaruhi beberapa simpul peradaban budaya dunia sejak lama.
Akhirnya, pandemi sekarang ini sewajarnya jadi refleksi serius para pengurus negara dan semua anak bangsa, untuk mengecek ulang pondasi warisan berbangsa-bernegara, dengan bercermin dari sejarah “kejayaan peradaban” nusantara, terutama kesadaran sebagai peradaban negara tropis. Tentu, dengan tetap hati-hati dan peka jebakan romantisme dan glorifikasi masa lalu.
Tujuan akhirnya, bangun dari lelap dan memutus gurita oligarki penjajahan budaya “sontoloyo,” baik versi lama, maupun bentuk-bentuk terbaru.
=======
*Tulisan ini telah dimuat di kanal media online Mongabay Indonesia pada 31 Desember 2020. Artikel asli bisa dikunjungi dengan meng-klik di sini.
**Penulis adalah peneliti dan pegiat Sajogyo Institute. Fellow researcher di Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB University, Bogor.
Keterangan foto: Aktifitas jual beli ikan di TPI Alok Maumere Kabupaten Sikka, NTT yang tampak sepi dibanding sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Sumber Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia.