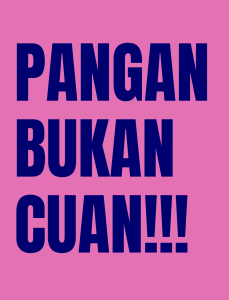Penulis: Eko Cahyono
“Bagi kita, rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit), karena rakyat itu jantung hati bangsa, dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka, semuanya itu bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur- penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya”
(Mohammad Hatta, Daulat Ra’jat, 20 September 1931 -Ejaan disesuaikan dengan EYD).
Kedaulatan Rakyat dan Mandat UUPA 1960
Semangat Indonesia Merdeka adalah “Kedaulatan Rakyat”. Bung Hatta dalam kutipan di atas menegaskan, tercapai tidaknya cita-cita ini menentukan tinggi rendahnya derajat Kita sebagai bangsa. Sebab, ibarat tubuh, rakyat adalah jantung dan hatinya bangsa. Semangat mewujudkan kedaulatan rakyat dilatarbelakangi oleh kebijakan Kolonial yang menindas, kejam, dan tidak manusiawi, di antaranya “Cultuur Stelsel” (tanam paksa), penerapan politik “Domain Negara” dalam Agrarische Besluit sebagai pelaksanaan Agrarische Wet 1870, dan seterusnya.
Prof. Boedi Harsono, SH. (seorang tokoh penting dalam perumusan UUPA 1960) memberikan ilustrasi keadaan itu dalam salah satu sub-bab bukunya dengan judul “Domein Verklaring memperkosa hak-hak rakyat pribumi”. Hal itu karena dampak pemberlakuan Domein Verklaring, itu adalah sarana mengambil tanah-tanah rakyat pribumi yang tidak memiliki tanda bukti tertulis. Tanah-tanah itu kemudian menjadi “Tanah Milik Negara”, yang dipergunakan untuk mendukung politik pertanahan ketika itu bagi kepentingan penanaman modal terutama sektor perkebunan secara besar-besaran.
Sistem ekonomi, politik dan sosial rezim kolonial telah menista hak dasar kemanusiaan, menindas dan menghisap manusia atas manusia yang lain dalam kurun ratusan tahun di nusantara. Kemderdekaan adalah pintu gerbang awal. Semangat cita-cita Kedaulatan Rakyat diikat secara hukum menjadi Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mendasarkan mandat konstitusional ini, maka salahsatu pilar utama dari cita-cita kedaulatan rakyat itu jelas terkait dengan kedaualatan agraria. Tepat di titik inilah sejarah berilku dan panjang dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5. 1960 dengan jalan perombakan struktural Reforma Agraria dirumuskan.
Merujuk Guru Agraria, Dr (HC) Gunawan Wiradi, bahwa sudah sejak awal, yaitu segera setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Para Pendiri Bangsa mulai mengupayakan untuk melakukan Refroma Agraria: merombak beragam ketimpangan struktural (kepemilikan, penguasaan, distribusi, akses dan pemanfaatan) atas sumber-sumber agraria warisan Kolonial, dengan cara merumuskan undang-undang agraria baru, yakni mengganti UU Agraria Kolonial 1870. Namun upaya itu terpaksa mengalami proses panjang selama 12 tahun. Meski akhirnya, lahir UUPA.
Proses panjang ini disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, Periode 1945-1950 adalah masa revolusi fisik. Perang dan damai silih berganti, sehingga kerja panitia penyusunan undang-undang menjadi tersendat-sendat. Kedua, Periode 1950-1960, sekalipun relatif adalah masa damai, namun gejolak politik masih juga silih berganti, sehingga kabinet pemerintah pun jatuh bangun. Panitia Agraria pun menjadi berganti-ganti: Panitia Agraria Yogya 1948; Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956; Panitia Sunaryo 1958; dan Rancangan Sadjarwo 1960. Ketiga, Partai-partai besar dalam DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berbeda-beda pandangannya mengenai agraria, sehingga titik temu atau kompromi sulit dicapai (Wiradi, 2005).
Penggalan konteks historis di atas menegaskan bagaimana jalan terjal, para Pendiri Bangsa pasca kemerdekaan politik dicapai, memikirkan cara bagaimana mengatur ulang sumber- sumber agraria dan kekayaan alam nasional kembali ke pangkuan pertiwi. Cita-cita kedaulatan rakyat dan agraria sebagai mandat Kemerdekaan Indonesia dicita-citakan dengan pondasi prinsip dan nilai-nilai keadilan dan tanpa penindasan manusia, khususnya dalam mengatur hubungan manusia dengan tanah dan sumber agrarianya di Indonesia.
UUD Negara RI 1945 Pasal 33 ayat (3), dan kemudian menjadi kaedah-kaedah pengaturan dalam UUPA 1960 menegaskan kewajiban memutus sejarah I’exploitation de I’homme par I’homme (eksploitasi manusia oleh manusia) tertuang dalam UUPA, antara lain melalui pasal 10 ayat 1; pasal 13 ayat 2 dan ayat 3; serta pasal 41 ayat 3. Sebab, menurut Pak Wiradi (2004), Para Pendiri Republik Indonesia dan para perumus UUPA-1960 sudah mempunyai “pandangan ke masa depan” (foresight) yang jauh (karena beliau-beliau itu pada umumnya belajar sejarah dan perjalanan sejarah), sehingga yang hendak diatur oleh UUPA itu bukan sebatas tanah tetapi “agraria”.
Dalam Pasal 1 (ayat 1 sampai ayat 5) UUPA 1960 jelas sekali rumusannya: “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya…! “inilah “agraria”! selain permukaan bumi, juga tubuh bumi di bawahnya (ayat 4); juga yang berada di bawah air. Dalam pengertian air, termasuk laut (ayat 5). Yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan ruang di atas air (ayat 6). Demikian pula Pasal 4 ayat 2. Atas dasar pemahaman di atas, maka istilah-istilah “sumber daya alam”, lingkungan”, “tata ruang” (dan lain-lainnya), semua itu pada hakekatnya hanyalah istilah-istilah baru untuk unsur-unsur lama yang sudah tercantum dalam UUPA.
Reforma Agraria dalam Kepungan Rezim Kontra Reforma Agraria
Urgensi reforma agraria adalah menata ketimpangan struktur agraria agar lebih berkeadilan, dengan tujuan: (1) Mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Menangani dan menyelesaikan konflik agraria; (3) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (4) Memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi; (5) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (6) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan (7) menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan ini mensyaratkan bangunan sistem ekonomi politik yang berwatak sosialisme-kerakyatan sebagaimana dijelaskan dalam mandat lahirnya UUD 1945 dan UUPA 1960. Tujuannya, mewudjukan kedaulatan rakyat, mengatur sumber-sumber agrarian demi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan prinsip keadilan sosial, menghapus penindasan dan penghisapan manusia atas manusia lain.
Tujuan sejati Reforma Agraria (RA) di atas penting ditegaskan kembali sebab banyak kelompok dan multi pihak memakai ‘topeng RA’ sebagai legitimatornya. Termasuk badan- badan donor dunia seperti World Bank misalnya. Karenanya mengenal konsep dasar dari RA menjadi penting. Setidaknya ada 4 tipe RA yang umum dikenal: (a) Market Lead Land Reform (RA yang dipandu pasar), (b) State lead Land Reform/Land Reform by Grace (RA yang dipandu oleh negara, (c) People/Peasant Lead Land Reform (RA yang dipandu oleh rakyat/petani), (d) Land Reform by Laverage (RA yang didongkrak dari bawah (oleh rakyat). Masing-masing konsep ini punya penjelasan dan batas ruang lingkupnya sendiri.
Dalam kasus di Indonesia, RA pernah dicanangkan kuat melalui mandate UUPA No. 5 tahun 1960. Namun, sebelum diiplementaskan secara utuh, putus secara politik karena huru hara politik nasional 1965. Hingga era Reformasi, RA belum sempat dipraktekkan dengan penuh. Sejak era SBY, kata Reforma Agraria muncul dan hadir kembali di ranah kebijakan nasional, terselip dalam program Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), namun sayang, dengan berbagai kondisi, praktiknya; layu sebelum berkembang.
Di agenda NAWACITA era Jokowi- JK kebijakan RA ekplisit diagendakan sebagai agenda strategis nasional. Sayang, praktiknya sekarang lebih dominan pada msalah administrasi pertanahan dan legalitas asset dengan program sertifikasi tanah. Terlebih pasca lolosnya UU No 11, 2020 tentang Cipta Kerja, terutama dengan agenda Bank Tanah, yang merupakan manifestasi neo-domeinverklaring menjadikan corak kebijakan atas nama dan klaim “Reforma Agraria” seperti ini, nampak lebih dekat karakternya pada jenis “Market-Led Land Reform (Land Reform yang dipandu oleh pasar)”.
Kebijakan ‘atas nama Reforma Agraria” dijalankan, namun ijin dan konsesi penyebab konflik agraria (Perkebunan, Petambangan, Kehutanan, dan Infrastruktur) diberi “karpet merah”. “Reforma Agraria” dikampanyekan, namun praktik land grabbing dan green grabbing penyebab kriminalisasi dan ketidakadilan kaum petani, nelayan, masyarakat adat, buruh (perempuan dan laki-laki) terus meningkat terjadi.
Singkatnya, jika prioritas program sertifikasi tanah dan legalisasi asset yang dijalankan, semestinya tidak perlu memakai “Reforma Agraria” sebab itu sudah menjadi TUPOKSI Kementrian ATR/BPN sejak semula. Reforma Agraria sebagaimana diuraikan di awal, mewajibkan semangat perombakan beragam ketimpangan struktural untuk mewujudukan kedaulatan rakyat dan agraria yang menjadi mandat Kemerdekaan sejak 76 tahun lalu.
Melanjutkan ‘Revolusi yang Belum Selesai?!’
Salah-satu cita-cita para Pendiri Bangsa setelah merdeka Indonesia adalah mampu lebih leluasa “Mendajung Dua Karang” (Hatta, 1948) yakni antara Sosialisme-Komunisme (Timur) dan Kapitalisme-Liberalisme (Barat) untuk menemukan demokrasi ekonomi dan politik ala Indonesia sendiri. Sayangnya, Kini setelah 76 Merdeka, justru berlabuh disalah satu karang, yakni sistem kapitalisme-neolliberalisme.
Menurut hemat penulis, secara singkat jawabnya adalah, karena revolusi politik yang melahirkan kemerdekaan, belum diikuti dengan satu bentuk “revolusi sosial-kebudayaan” atau dengan sebutan nama lain yang punya tujuan sejenis. Pasca Merdeka, Orba dan Pasca Reformasi belum ada “kesempatan” serius untuk melakukan perombakan mendasar itu, termasuk dalam melaksanakan Reforma Agaria (sejati). Akibatnya yang hadir, beragam bentuk-bentuk penjajahan baru dalam ranah pengetahuan, paradigma kebijakan pembangunan, pendidikan, politik-ekonomi, dan kebudayaan.
Maka, untuk menutup tulisan ini ijinkan mengutip tulisan “terakhir” Pak Gunawan Wiradi, sebelum wafatnya, sebagai renungan bersama, yang berjudul “Renungan Seorang Lansia: Kondisi Poleksosbud Indonesia Sejak Beberapa Dasa Warsa Terakhir”: …. “Tetapi, apakah itu berarti sebenarnya Revolusi belum selesai? Jika begitu, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara menyelesaikannya? Sementara itu, sekarang ini, bicara soal Revolusi saja terasa sudah ditabukan, karena mungkin diasosiasikan dengan kemungkinan menjadi terorisme. Teori-teori tentang Revolusi agaknya perlu dipelajari kembali. Sebab, tidak ada Revolusi yang berhasil tanpa teori Revolusi. Benarkah?” (Wiradi, 15 Mei 2020).
====
Tulisan ini telah dimuat dalam rubrik Opini pada Buletin Bina Desa. Edisi No.139/XL/2021. Soft file opini ini dapat diunduh di sini.