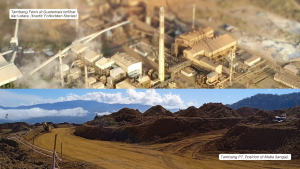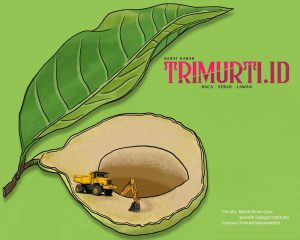Hampir empat bulan lalu (3/6) Indonesia kehilangan putra terbaiknya, Prof. Sediono M.P. Tjondronegoro. Dijuluki sebagai ‘professor-nya kaum tani’, fokus keilmuan tidak bisa lepas dari keberpihakan kepada kaum tani Indonesia, khususnya petani gurem dan buruh tani.
Begitulah gambaran besar gagasan pemikiran Sediono M.P. Tjondronegoro. Pemikiran beliau yang begitu banyak, kaya-perspektif dan berpihak kepada golongan paling lemah di pedesaan agaknya masih belum banyak yang digali. Pada Senin (1/9), Sajogyo Institute kembali mengadakan Serial Diskusi Tematik Online (SINEMATIK) #14 mengangkat tema “Membedah Pemikiran Sediono M.P. Tjondronegoro”.
SINEMATIK #14 dimoderatori oleh Ganies Oktaviana (Peneliti Sajogyo Institute) dan mengundang dua pembicara, Dr. Soeryo Adiwibowo (Dosen FEMA IPB) dan Aprilia Ambarwati (Peneliti AKATIGA).
Soeryo Adiwibowo sebagai pembicara pertama, kembali menekankan konsep pemikiran Tjondronegoro dalam disertasinya yang telah dicetak Oxford University Press (1984), yaitu konsep Sodality, yaitu daya kuat ikatan sosial khas pedesaan yang masih mendasarkan daya perekatnya pada nilai tolong menolong.
Bagi Pak Bowo, sapaan akrab Soeryo, Tjondronegoro ingin menggali lebih dalam sampai level mana ikatan-ikatan sosial yang masih berlandaskan nilai tolong menolong masih terdapat. Dari berbagai usaha secara kualitatif dan kuantitatif, ditemukan bahwa ikatan sosial tersebut masih terdapat di tingkat dusun atau dukuh.
Hal ini selaras dengan pengalaman pak Bowo terhadap beberapa unit kecil yang terdapat di Aceh. “Apabila saya lihat di Aceh, unit terkecil adalah Gampong atau Kampong-Kampong yang memiliki ikatan sosial yang lebih kecil lagi, misalnya untuk ikatan warga desa yang bekerja atau mengakses kawasan hutan di dalam gampong di sekitarnya, ikatan tersebut dipimpin dan diikat oleh Panglima Uten. Apabila nelayan di kampong itu pada level terkecil, itu ada Panglima Laot”, ungkap Pak Bowo.
Berbagai ikatan sosial kecil masyarakat Aceh tersebut ada yang berdasarkan mata pencaharian, tempat nafkah, lalu diikat hingga ke level kampong dan level lebih atas. Bagi Pak Bowo, karena ikatan yang kuat di tingkat paling kecil hingga ke atas (bottom-up) seperti itu, Belanda sulit menaklukkan Aceh.
Meski begitu, perlu untuk mengakui adanya beberapa kekurangan dalam konsep tersebut, yaitu penggunaan data sekunder dan mencakup pada dua kecamatan di Jawa sehingga potret empiris di lain tempat bisa jadi berbeda. Meski begitu, yang menjadi perhatian bersama adalah masalah kepemimpinan sebagai faktor penting dalam ikatan-ikatan sosial di desa.
Aprilia Ambarwati, sebagai pembicara kedua, mengenang kembali pribadi Tjondronegoro yang luar biasa, bangsawan yang egaliter dan sosok pembelajar dengan pengalaman dari seorang Tentara Pelajar menjadi seorang Professor Kaum Tani (pengalaman beliau diselamatkan oleh petani kecil saat Tjondronegoro terkena ledakan granat saat pertempuran Revolusi Kemerdekaan 1945-1949).
Konsep Sodality menjadi inspirasi bagi Lia, sapaan akrab Aprilia, sebagai peneliti di AKATIGA. Tjondronegoro, yang memfokuskan diri menyelesaikan masalah kelompok marginal miskin pedesaan dengan bertitik tolak dari konsep sodality. Dengan konsep Sodality, Tjondro ingin menekankan bahwa pembangunan sosial ekonomi bangsa tidak bisa (dan tidak boleh) lepas dari akar di bawa, yaitu masyarakat desa.
“…Namun, dengan sentralisme, yang timbul struktur sosial berlapis-lapis sehingga sodalis mengalami disintegrasi,” ujar Lia mengutip Tjondronegoro. Struktur sosial ini menjadi tantangan untuk para peneliti, bagaimana konsep sodalitas ini menjadi dasar konsep mengurai permasalahan, walaupun struktur sosialnya sangat kompleks.
Pemikiran Tjondronegoro juga memberikan inspirasi bagi para peneliti di AKATIGA dalam menjawab beberapa problem yang ditemui di desa. Lia mengambil beberapa contoh seperti masalah ketahanan dan kekuatan pangan skala kecil di desa dan masalah ketimpangan penguasaan lahan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengaturan akses tanah kas desa sebagai bentuk usaha mengurangi ketimpangan penguasaan dan akses lahan pertanian dan mengembangkan karang taruna untuk ikut membangun pertanian di desa menjadi langkah awal untuk membuka jalan bagi para pemuda memulai kembali usaha bertani di desa.
Hal ini berangkat dari inspirasi pemikiran Tjondronegoro yang gelisah terhadap kaum muda tidak lagi mengenali kerja pertanian di pedesaan, mengenal dan mengetahu desa, dusun, dukuh dan kecamatan hanya sebatas melalui buku tanpa bisa mengalaminya sendiri melalui tangan, kaki dan tubuhnya. Di sisi lain, petani di Indonesia telah mengalami penuaan (aging), yaitu rata-rata usia petani di atas 45 tahun (BPS, 2013).
Sedangkan permasalahan yang ingin dijawab oleh pengambil kebijakan seringkali timpang terhadap kenyataan di lapang. Menjawab masalah pertanian di Indonesia tidak hanya terbatas pada transfer dan akses teknologi pertanian semata, namun harus dilihat perpindahan sumber agraria, tingkat pengetahuan dan keterampilan dan hal lainnya terkait masalah agraria di lapang. Seperti, masalah teknologi juga telah berdampak semakin terpinggirkannya tenaga kerja perempuan di desa yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.
“Menurut pak Tjondro kita harus menulis dengan jujur dan menyuarakan dengan benar, karena kegelisahan yang kira rasakan itu kadang tidak dirasakan oleh para pengambil kebijakan, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan ataupun pengambilan kebijakan bisa dengan menggunakan penelitian yang telah dibuat”, jelas Lia.
Unduh Bahan Materi:
Aprilia Ambarwati – Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro: Pemikiran yang Masih Relevan